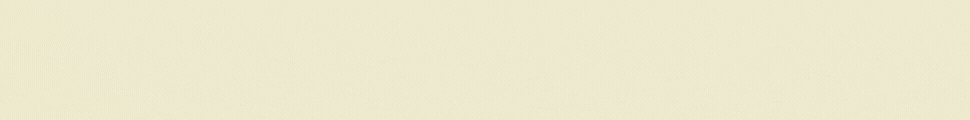JEJAK KENANGA 2: PEREMPUAN DALAM SEKAPAN
Ruangan itu gelap, bau lembap bercampur anyir menyergap hidung. Kenanga membuka matanya perlahan. Kepalanya masih berdenyut, pergelangan tangannya terasa panas, bekas tali yang mencengkeram erat.
Dari sudut matanya, ia melihat tetesan air jatuh dari pipa bocor di langit-langit. Ia menggerakkan pergelangan tangannya sedikit—masih terikat.
Langkah berat mendekat. Lantai kayu tua berderit di bawah sol sepatu bot yang kasar.
“Sial.”
Kenanga tetap diam, mengatur napasnya. Ia menajamkan pendengaran, menghitung jumlah langkah—satu orang. Suara pintu besi berdecit saat dibuka. Cahaya lampu neon redup menerobos masuk, mengiris gelapnya ruangan.
Seorang pria bertubuh besar berdiri di ambang pintu, tatapannya dingin. Bekas luka membelah pelipis kirinya.
“Bangun.”
Suara beratnya memecah keheningan. Kenanga mengangkat kepalanya, menatap pria itu dengan sorot mata tajam.
“Lu pikir bisa main-main sama kami?”
Kenanga tersenyum miring, meski tubuhnya terasa lemah. “Kalau kalian pikir ini bakal menghentikan gue, kalian salah besar.”
Pria itu menyeringai, lalu melangkah mendekat. “Semangat lu bagus, sayang. Tapi semangat gak akan nyelametin lu.”
Tangan kasarnya menarik kursi kayu, menyeretnya hingga mengeluarkan bunyi nyaring. Ia duduk, mencondongkan tubuh ke depan.
“Kita langsung ke intinya aja. Siapa yang nyuruh lu ngelacak kita?”
Kenanga tetap diam.
Sebuah tamparan keras mendarat di wajahnya. Kepala Kenanga tersentak ke samping, tapi matanya tetap dingin.
“Sialan…” pria itu mendecak, lalu menoleh ke belakang. “Bawa dia ke tempat lain. Kita lihat seberapa kuat dia bertahan.”**
Dua pria masuk dan menarik Kenanga berdiri. Tapi di sela langkah, matanya menangkap sesuatu—pecahan kaca kecil, hanya beberapa sentimeter dari ujung sepatunya.
“Ini dia.”
Dengan gerakan kecil yang tersamar, Kenanga menggeser kakinya, menarik pecahan kaca itu lebih dekat.
Di tempat lain, Reno berlari di tengah hujan gerimis, napasnya tersengal. Tangannya gemetar saat menghubungi Kinan.
“Kenanga diculik!” suaranya hampir berteriak. “Gue nggak tahu harus gimana!”
Dari seberang telepon, Kinan terdiam sesaat. Lalu, dengan suara yang tetap dingin, ia berkata:
“Diam dulu. Jangan panik. Gue bakal gerakin orang buat cari dia.”
Sementara itu, Kenanga menatap lantai. Di sana, hanya berjarak beberapa sentimeter dari ujung sepatunya—pecahan kaca kecil.
Ia mengambil napas panjang, menutup matanya sejenak. Lalu mulai menggeser tangannya perlahan.
Gue nggak akan diam.
*****
“Mereka menculik anak-anak. Anak saya hilang seminggu lalu… Polisi bilang bakal cari, tapi sampai sekarang nggak ada kabar!”
Suara perempuan itu bergetar. Wajahnya kusut, matanya sembab. Tangannya menggenggam erat foto seorang gadis belasan tahun, tersenyum manis dalam seragam sekolah.
Kenanga menatap foto itu lama. Di sebelahnya, Kinan duduk tegak, tangannya bertaut di atas meja. Kantor IndependenNews terasa sunyi, hanya suara jam dinding yang berdetak pelan.
“Ini bukan kasus pertama,” Kinan akhirnya bersuara. “Aku sudah melacak, ada pola. Anak-anak gadis, mayoritas dari keluarga sederhana, menghilang tanpa jejak. Beberapa ditemukan… tapi dalam keadaan yang mengenaskan.”
Kenanga menoleh cepat. “Maksud Bang Kinan?”
Kinan menekan beberapa tombol di laptopnya. Layar menunjukkan foto-foto yang tidak dipublikasikan—tubuh perempuan muda yang ditemukan di sungai, di pinggir jalan, di dalam peti. Wajah mereka tertutup, tapi ada satu kesamaan. Bekas jahitan panjang dari dada ke perut.
“Mereka diambil organnya,” Kinan melanjutkan. “Dan ini lebih besar dari yang kita kira. Ada jalur perdagangan manusia yang mengarah ke luar negeri. Jaringan kami mencium ada permainan orang-orang penting.”
Ruangan hening.
Kenanga menyandarkan tubuhnya, matanya menatap layar dengan rahang mengatup. “Berapa banyak korban?”
Kinan menghela napas. “Yang dilaporkan? Puluhan. Yang sebenarnya? Bisa ratusan.”
Kenanga mengepalkan tangan. “Kita harus ungkap ini.”
Kinan menatapnya dalam. “Jangan gegabah. Ini bukan sekadar mafia jalanan. Mereka punya uang, punya kekuasaan.”
Kenanga mencondongkan tubuh. “Justru itu. Aku bisa masuk. Aku bisa jadi umpan.”
Kinan terdiam sesaat, lalu menggeleng. “Terlalu berbahaya, Kenanga.”
“Kalau kita tidak melakukan sesuatu, siapa lagi?” Kenanga bersikeras. “Aku bisa atur strategi. Aku masuk sebagai target, biar mereka culik, dan kita bongkar dari dalam.”
Kinan mendesah. “Ini gila.”
Kenanga tersenyum tipis. “Bang Kinan sendiri yang bilang, aku tidak bisa diam melihat ketidakadilan.”
Tiga hari kemudian…
Kenanga berjalan di trotoar sebuah jalan sepi. Malam mulai larut. Sebuah mobil hitam melambat di belakangnya.
Lalu segalanya gelap.
*****
Lampu neon berkedip redup di luar, memantulkan bayangan samar ke dalam kamar kecil berbau rokok dan alkohol basi. Seorang pria duduk di tepi ranjang, menatap ponselnya yang bergetar di atas meja kayu usang.
Ia mengangkatnya tanpa suara.
“Target sudah bergerak,” suara di seberang terdengar datar. “Eksekusi sesuai protokol.”
Mata pria itu menyipit sedikit, jari-jarinya mengetuk permukaan meja dengan ritme teratur. “Lokasi?”
“Gudang tua, pinggiran kota. Waktu berjalan. Pastikan dia keluar hidup-hidup.”
Pria itu tak menjawab, hanya mematikan panggilan. Lalu, ia berdiri, menarik jaketnya, dan menyisipkan pistol ke balik pinggang. Matanya gelap, penuh perhitungan.
Ia tidak pernah mempertanyakan perintah. Tapi kali ini, ada sesuatu yang berbeda.
Sosok yang harus ia selamatkan… bukan orang biasa.
Tanpa suara, ia meninggalkan kamar, menyusuri lorong sempit motel kumuh itu. Begitu ia melewati resepsionis, si penjaga yang setengah tertidur hanya sempat melihat bayangan gelap sebelum pria itu menghilang di tengah hujan yang mulai turun.
Misi dimulai.
*****
Ambar mondar-mandir di ruang tamu, tangannya gemetar saat meremas ponselnya yang sunyi. Tidak ada kabar dari Kenanga. Tidak ada pesan. Tidak ada panggilan.
Reno duduk di sofa, mencoba menyembunyikan kegelisahannya sendiri. “Tante, tenang dulu. Kenanga itu hebat. Dia jago silat, nggak mungkin kalah begitu aja.”
Ambar berhenti melangkah, menatap Reno dengan mata merah. “Jago silat? Reno, ini penculikan! Bukan tanding di gelanggang!” Suaranya bergetar. “Kalau mereka bawa senjata? Kalau—”
“Tante…” Reno bangkit, menahan bahu Ambar dengan lembut. “Kenanga nggak sendirian. Bang Kinan udah gerakin orang buat nyari dia. Dan gue yakin banget, dia pasti ngasih mereka perlawanan.”
Ambar terisak, menutupi wajah dengan kedua tangan. “Dia anakku satu-satunya, Reno… Aku nggak mau kehilangan dia.”
Reno menggenggam tangannya erat. Dalam hati, ia pun takut—takut setengah mati. Tapi kalau dia ikut panik, siapa yang bisa diandalkan Ambar?
“Kita percaya sama Kenanga, Tante.” Reno berusaha tersenyum. “Dia itu perempuan di ujung bara. Api nggak bakal membakarnya.”
Ruang tamu rumah Ambar dipenuhi ketegangan. Hanya ada suara jarum jam berdetak dan sesekali helaan napas berat.
Puspita berdiri dengan tangan terlipat di dada, matanya tajam menatap Reno yang duduk dengan wajah penuh rasa bersalah.
“Lo yang selalu sama Kenanga! Lo harusnya bisa cegah dia!” suara Puspita meninggi, penuh emosi yang ia coba tahan.
Reno mengusap wajahnya dengan kasar. “Lo pikir gue nggak nyoba? Ini Kenanga, Pus. Sekali dia mutusin sesuatu, nggak ada yang bisa nahan.”
Puspita menghela napas panjang, berusaha menenangkan diri. “Kalau sesuatu terjadi sama dia…”
Ambar menyentuh bahunya dengan lembut. “Pus, Nak… Ibu tahu kamu sayang sama Kenanga. Tapi jangan menyalahkan dirimu sendiri.”
Puspita menggeleng pelan. “Bukan soal nyalahin diri sendiri, Bu. Aku cuma nggak terima Kenanga sendirian di luar sana, sementara kita cuma bisa duduk di sini.”
Reno menyandarkan kepalanya ke sofa, matanya menatap langit-langit. “Lo pikir gue nggak ngerasa kayak gitu?”
Puspita menarik napas dalam, mencoba mengendalikan pikirannya yang berputar cepat. “Bang Kinan pasti lagi gerak sekarang.”
Reno menoleh cepat. “Kinan? Lo udah kontak dia?”
Puspita mengangguk mantap. “Aku tahu dia nggak bakal tinggal diam. Dia ngerti betul situasi ini lebih dari siapa pun.”
Di antara mereka bertiga, Puspita yang paling paham dunia bayangan yang sedang Kenanga hadapi sekarang.
Sebagai mahasiswa di Sekolah Tinggi Intelijen Negara, ia tahu betapa berbahayanya jaringan yang sedang mereka sentuh. Ini bukan sekadar penculikan biasa.
Ambar menarik napas berat. “Pus, kalau kamu ada cara buat bantu… lakukan.”
Puspita menatap ibu angkatnya itu, lalu mengangguk. Ia tak akan membiarkan Kenanga sendirian. Tidak sekarang. Tidak pernah.
*****
Kenanga merasakan perih di pergelangan tangannya yang lecet akibat tali yang telah ia putus dengan pecahan kaca. Tapi ia tak punya waktu untuk memikirkan itu. Dua pria berbadan besar telah menyadari bahwa ia bebas.
Tanpa aba-aba, pria pertama menyerang dengan tinju mengarah ke wajahnya. Kenanga menghindar dengan gerakan cepat, tubuhnya merunduk sebelum melesat maju.
Siku kerasnya menghantam rahang pria itu, membuatnya terhuyung. Tapi yang kedua sudah menyerang dari belakang.
Kenanga berbalik, kakinya menendang kursi kayu di lantai, meluncurkannya ke arah lawan. Pria itu tersandung, dan dalam hitungan detik, Kenanga sudah melompat, lututnya menghantam wajahnya. Bunyi tulang patah terdengar jelas.
Dua orang lagi masuk ke ruangan. Satu membawa pisau. Kenanga memutar tubuhnya, menghindari tusukan yang hampir mengenai perutnya.
Ia menangkap pergelangan tangan pria itu, memutarnya keras hingga terdengar bunyi sendi bergeser, lalu merampas pisaunya. Tanpa ragu, ia menancapkannya ke paha pria itu.
Pria kedua menyerang dengan batang besi, mengayunkannya ke arah kepala Kenanga. Ia menunduk, lalu berputar dengan tendangan rendah yang membuat pria itu jatuh tersungkur.
Darah mulai bercipratan di lantai. Napas Kenanga berat, tapi ia tak berhenti. Ini baru awal.
Lalu, pintu ruangan terbuka lebar.
Masuklah tiga orang.
Robert, pria berotot dengan rahang baja, seorang petinju brutal yang pernah bertarung di bawah tanah.
Masimura, pria Jepang berusia 40-an dengan tatapan dingin, seorang karateka yang dikenal tanpa belas kasihan.
Dan Joe Han, petarung Muay Thai dari Thailand dengan tubuh penuh tato.
Kenanga mengatur napasnya. Tiga lawan berat dalam satu waktu.
Robert, Masimura, dan Joe Han berdiri mengelilingi Kenanga. Mereka saling berpandangan, seolah sedang menentukan siapa yang akan menghajar perempuan ini lebih dulu.
Robert, pria bertubuh besar dengan kepala plontos dan rahang kotak, tertawa kecil sambil menggulung perban di tangannya. “Gue duluan, lah. Kasih pemanasan dikit.”
Joe Han terkekeh, menyesap rokoknya sebelum membuangnya ke lantai. “Jangan langsung bikin dia pingsan, Rob. Gue juga mau main.”
Masimura, lelaki Jepang dengan ekspresi datar, hanya mengangguk kecil. “Lakukan cepat. Kita tak punya banyak waktu.”
Kenanga berdiri di tengah lingkaran mereka, napasnya teratur. Matanya tajam mengamati setiap gerakan. Tangan-tangannya masih terasa sakit akibat borgol yang tadi ia lepaskan dengan paksa. Namun, ia tak peduli.
Robert maju, mengepalkan tinjunya. “Ayo, cewek manis. Tunjukin apa yang lo bisa.”
Kenanga tersenyum miring. “Lo bakal nyesel.”
Tanpa aba-aba, Robert melepaskan jab cepat ke arah wajahnya. Kenanga menghindar dengan sedikit memiringkan kepala, tapi tak menyangka pukulan kedua sudah menanti. Tinju keras menghantam lengannya, membuatnya terhuyung sedikit ke samping.
“Sial,” gumamnya, merasakan nyeri menjalar.
Robert tak memberi jeda. Ia melancarkan hook ke arah perut Kenanga, namun perempuan itu memutar tubuhnya, menangkis dengan siku, lalu menyelip di bawah lengannya. Dalam hitungan detik, ia melesat ke belakang Robert dan menendang lututnya.
Robert terhuyung. “Brengsek!”
Ia berbalik, mengayunkan pukulan mematikan. Kenanga menunduk, lalu menyarangkan sikut keras ke tulang rusuknya. Robert menggeram, tapi masih berdiri.
“Cukup, Rob.” Masimura akhirnya melangkah maju. “Kau terlalu lambat.”
Robert mendecak, lalu mundur.
Masimura membuka jaketnya, memperlihatkan tubuh yang terlatih. “Aku akan menghabiskan ini dalam tiga gerakan.”
Kenanga menelan ludah. Berbeda dengan Robert yang mengandalkan kekuatan, Masimura bergerak dengan tenang, penuh perhitungan.
Tiba-tiba, ia menghilang dari pandangan.
BRUK!
Sebuah tendangan cepat menghantam bahu Kenanga, membuatnya terpelanting ke belakang. Ia nyaris jatuh, tapi berhasil bertumpu pada satu tangan dan berputar di udara sebelum mendarat dengan kokoh.
Masimura tersenyum tipis. “Menarik.”
Kenanga tidak menjawab. Ia menggeser kuda-kudanya, mengatur napas.
Masimura menyerang lagi, kali ini dengan kombinasi pukulan dan tendangan yang mematikan. Kenanga menangkis beberapa, tapi beberapa kali terkena serangan di perut dan pinggang. Rasa sakit mulai merayapi tubuhnya.
Namun, ia bukan perempuan lemah.
Saat Masimura melompat untuk menyerang dengan tendangan berputar, Kenanga menunduk, lalu menyapu kakinya dari bawah. Masimura kehilangan keseimbangan dan terjatuh.
Kenanga langsung bergerak, menyarangkan lutut ke dadanya. Masimura mengerang, tapi dengan cepat menangkap kaki Kenanga dan membantingnya ke lantai.
Darah merembes di sudut bibir Kenanga. Ia tersenyum sinis.
Joe Han menepuk bahu Robert. “Dia kuat. Sekarang, giliran gue.”
Kenanga berusaha bangkit, tapi Joe Han sudah lebih dulu melompat dan mengayunkan tendangan keras ke arah wajahnya. Kenanga mengangkat tangan untuk menangkis, tapi dampaknya tetap terasa brutal.
Ia terhuyung ke belakang, lututnya hampir menyentuh lantai.
Joe Han berdecak. “Capek, Sayang?”
Kenanga mengangkat wajah. Matanya tetap tajam, meski tubuhnya terasa remuk. “Lo banyak omong.”
Joe Han tertawa, lalu menyerang dengan serangkaian tendangan cepat. Kenanga berusaha menghindar, tapi kecepatannya luar biasa. Beberapa serangan mengenai bahunya, perutnya, bahkan rahangnya.
Kenanga jatuh terduduk, tangannya bertumpu pada lantai.
Robert tertawa. “Udah selesai?”
Saat Kenanga berusaha bertahan dari pukulan dan tendangan Joe Han, Robert dan Masimura berdiri santai, menunggu giliran.
Namun tiba-tiba—
DOR!
Lampu gudang pecah berhamburan.
Suasana berubah gelap.
Lalu, terdengar suara langkah pelan… ritmis… mendekat dari bayangan.
Seorang pemuda berbaju hitam muncul. Tegap. Tatapannya dingin.
Masimura menyipitkan mata. “Siapa lu?”
Pria itu tak menjawab. Dalam hitungan detik—
DOR!
Seorang penjaga yang mencoba mendekat jatuh dengan kepala tertembus peluru.
Robert menggeram. “Sial! Bunuh dia!”
Masimura dan Robert bergerak serentak. Tapi pria berbaju hitam itu menghindar dengan gesit, membalas dengan gerakan cepat dan brutal.
Tendangan tajam menghantam dada Robert, membuatnya terpental menabrak meja.
Masimura mencoba menyerang dari samping—tapi pria itu lebih cepat. Siku menghantam dagu Masimura, diikuti dengan sapuan kaki yang membuatnya jatuh keras.
Pemuda itu tak berkata sepatah kata pun. Hanya gerakan cepat, mematikan.
Kenanga, yang masih berhadapan dengan Joe Han, melihat sekilas pria misterius itu.
“Siapa dia…?”
Tapi tak ada waktu untuk bertanya. Joe Han kembali menyerang. Dan pertarungan terus berlanjut..
*****
Suara mesin meraung pelan. Mobil SUV hitam melaju kencang di jalanan kota yang mulai lengang. Kinan duduk di kursi depan, wajahnya serius menatap layar tablet kecil yang dibawa Puspita.
Reno di belakang, tangannya tak henti-henti meremas celana jeansnya. Sementara Bima, seorang mantan perwira yang kini bekerja sebagai investigator independen, duduk dengan tangan terlipat di dada.
“Kita makin dekat,” suara Puspita dingin, matanya terpaku pada titik merah yang berkedip di layar.
Kinan melirik sekilas. “Kamu yakin ini Kenanga?”
“Seratus persen.” Puspita menekan layar, memperbesar peta digital. “Dia pakai smartwatch yang aku kasih waktu ulang tahunnya. Aku sengaja instal GPS rahasia. Dan sekarang dia di sini.” Ia menunjuk titik koordinat di luar batas kota.
Reno membungkuk, matanya membesar. “Gila, itu di gudang kosong?!”
Bima mengangguk pelan. “Tempat yang sempurna buat kerja kotor. Minim saksi, gampang dibersihkan kalau ada… sisa-sisa.”
Sunyi sejenak. Puspita menggigit bibirnya, matanya menegang. “Kalau kita terlambat…”
“Kita nggak akan terlambat,” potong Kinan cepat. “Bima, kita butuh akses. Bisa masuk tanpa bunyi?”
Bima menyeringai. “Tinggal bilang kapan.”
Puspita mengalihkan pandangannya ke Reno. “Lo siap, Ren?”
Reno menelan ludah. “Jujur aja, enggak. Tapi gue nggak bakal ninggalin Kenanga.”
Kinan mengangguk pelan. “Bagus. Kita main cepat, diam, dan kalau perlu—brutal.”
Mobil semakin mendekati titik lokasi. Napas mereka tertahan. Malam ini, mereka bukan sekadar sahabat yang mencari teman—mereka adalah pemburu yang masuk ke sarang serigala.
*****
Suasana kantor polisi tetap sibuk. Telepon berdering, suara keyboard terdengar cepat, dan petugas berseliweran dengan ekspresi serius.
Di sudut ruangan, Ambar masih duduk, tatapannya kosong, cangkir kopinya tetap dingin di tangannya.
Di seberangnya, seorang perwira wanita berseragam rapi berdiri dengan kedua tangan bertaut di depan. AKP Sulastri, Kepala Satuan Reserse Kriminal, menatap mantan komandannya dengan mata berkabut emosi.
“Bu Ambar…” Sulastri berusaha menjaga nada suaranya tetap lembut.
Ambar mengangkat kepalanya, menatap Sulastri dengan alis berkerut. “Kamu… siapa?”
Pertanyaan itu menusuk Sulastri lebih dalam dari yang ia duga. Tapi ia tetap tersenyum tipis. “Saya Sulastri, Bu. Dulu saya anak buah Ibu di kepolisian.”
Ambar masih diam, seolah berusaha menggali sesuatu dari pikirannya yang berlubang. Lalu samar-samar, kilatan memori datang.
“Sulastri…” gumamnya. “Kamu yang dulu sering aku marahi karena laporanmu berantakan.”
Sulastri tersenyum. “Betul, Bu. Dan Ibu selalu bilang kalau saya terlalu lamban untuk jadi detektif.”
Ambar menghela napas panjang. “Aku ingat sedikit. Tapi… tidak lama lagi aku akan lupa lagi, kan?”
Sulastri mengangguk pelan. “Mungkin, Bu. Tapi saya di sini. Saya akan tetap mengingatkan Ibu.”
Ambar memejamkan mata, meremas pelipisnya. “Kenanga… putriku. Dia menghilang. Aku harus menemukannya.”
Sulastri menarik kursi dan duduk di sebelahnya. “Bu… kami sudah bergerak. Tim sudah turun ke lapangan.”
“Sudah?” Ambar menatap Sulastri tajam, lalu melirik buku catatan kecil di tangannya. Tangannya gemetar saat membuka halaman terakhir yang ia tulis.
“Kenanga diculik. Jangan lupa. Cari Kenanga.”
Tinta masih baru. Ia menuliskannya tadi pagi. Atau mungkin beberapa jam lalu.
Sulastri melihat tulisan itu, lalu menatap Ambar dengan iba. “Ibu sudah ke sini kemarin… dan sehari sebelumnya juga.”
Dunia Ambar seakan runtuh dalam diam. Ia merasa terjebak dalam lingkaran waktu yang tidak memberinya kesempatan untuk bergerak maju.
“Aku tidak bisa… Aku tidak bisa lupa lagi. Aku harus menemukannya sebelum semua ini hilang dari kepalaku!” suaranya pecah, matanya berkaca-kaca.
Sulastri menepuk bahu mantan komandannya dengan lembut. “Saya janji, Bu. Saya tidak akan berhenti sampai kita menemukan Kenanga.”
Ambar menatapnya, ragu, takut. Tapi di mata Sulastri, ia melihat keteguhan yang sama seperti dulu—keteguhan yang pernah ia tanamkan pada anak buahnya.
Di luar sana, di suatu tempat yang gelap dan berbahaya, Kenanga sedang berjuang untuk hidupnya. Dan Ambar tahu, meskipun pikirannya bisa mengkhianatinya, ia tidak akan berhenti berjuang untuk mengingatnya.
*****
Asap tipis masih mengepul dari moncong pistol seorang pemuda tegap. Robert melirik bahunya yang berdarah.
Tembakan itu bukan untuk membunuh, tapi cukup untuk membuatnya sadar—lawan mereka bukan orang sembarangan.
“Lo siapa?” tanya Robert, matanya menyipit.
Pemuda itu tidak menjawab. Hanya satu langkah maju, perlahan, gerakannya seperti bayangan yang mengintai.
Masimura mengambil sikap kuda-kuda, tubuhnya tegang. “Jangan remehkan dia. Aku bisa merasakannya… Dia bukan orang biasa.”
Joe Han, yang masih berhadapan dengan Kenanga, menyeringai. “Terserah lo. Yang ini masih punya nyawa buat gue habisi.”
Kenanga mengangkat kedua tangannya, darah mengalir dari bibirnya, tapi matanya menyala penuh semangat.
Joe Han meluncurkan serangan lebih agresif. Tendangan cepat menghantam Kenanga, tapi kali ini dia sudah siap. Ia merunduk, memutar tubuhnya, dan membalas dengan sapuan kaki rendah.
Joe Han terjatuh, tapi langsung berputar di lantai dan bangkit dengan satu gerakan mulus.
“Bagus,” katanya sambil mengusap dagunya. “Tapi belum cukup.”
Joe Han melompat, melayangkan flying knee ke arah kepala Kenanga.
Duk!
Kenanga berhasil mengangkat lengannya, menahan serangan, tapi dampaknya membuatnya terdorong beberapa langkah ke belakang.
Joe Han tak memberi celah, ia berputar dan menghantam Kenanga dengan elbow strike ke arah pelipis!
Kenanga nyaris terjatuh. Pandangannya buram.
Tidak. Gue gak boleh kalah.
Dengan sisa tenaga, Kenanga meraih lengan Joe Han, menariknya ke bawah, dan membantingnya ke lantai dengan teknik silat “Guntingan Harimau”!
BRAK!!
Joe Han menghantam lantai keras, tubuhnya menegang.
Kenanga melompat ke atasnya, menghujani Joe Han dengan pukulan bertubi-tubi ke wajahnya—
Dug! Dug! Dug!
Darah muncrat. Joe Han tak bisa bergerak lagi.
Kenanga terengah-engah, lalu menoleh.
Pemuda misterius itu masih berdiri tegap, dikelilingi Robert dan Masimura.
Robert menggeram. “Gue bakal remukkin lo, bocah!”
Dia berlari menerjang, melayangkan pukulan seperti palu godam.
Pemuda itu tetap diam.
Secepat kilat, ia berputar ke samping, menghindari pukulan itu, lalu menendang lutut Robert dari samping—
KRAK!
Robert menjerit. Lututnya tertekuk dengan cara yang salah.
Pemuda itu tak memberi kesempatan. Ia melompat, lututnya menghantam dagu Robert.
Duk!
Robert terjungkal ke belakang, tak sadarkan diri.
Masimura melihat celah. Dia menyerang dengan kecepatan luar biasa, pukulan lurus mengarah ke tenggorokan Pemuda itu!
Dia mengangkat tangan, menangkis dengan siku, lalu menangkap pergelangan Masimura.
Dalam sekejap, dia memutar tubuh Masimura dan mengunci lengannya.
“Gue benci karate,” gumam Pemuda itu.
KRAKK!!
Tulang lengan Masimura patah. Jeritannya menggema di ruangan.
Dia mendorongnya ke lantai. Masimura menggeliat kesakitan, tidak bisa bertarung lagi.
Gudang itu hening.
Dua lawan tersungkur. Hanya suara napas berat Kenanga dan desingan peluru dari luar yang terdengar.
Kenanga berdiri di tengah ruangan yang berantakan. Darah mengalir dari sudut bibirnya, napasnya berat, tapi matanya tetap tajam.
Di seberangnya, seorang pemuda tegap berbaju hitam berdiri tenang. Wajahnya tetap misterius, tak menunjukkan emosi.
Sorot matanya dingin, tapi gerakannya tadi menunjukkan keahlian yang tak main-main.
Kenanga menatapnya, mengamati setiap detail.
“Lo baik-baik aja?” suara pemuda itu terdengar datar.
Kenanga meludah ke samping, menghapus darah dari bibirnya. “Gue bisa lebih baik kalau lo datang lebih cepat.”
Pemuda itu hanya menyeringai tipis.
Tapi sebelum mereka bisa berbicara lebih jauh—
BRAAK!!
Pintu gudang meledak.
Sekelompok orang bersenjata masuk, berseragam hitam.
Kenanga langsung bersiap bertarung lagi, tangannya mengepal, tapi pemuda berbaju hitam itu mengangkat tangan, memberi isyarat agar ia tetap tenang.
“Tenang,” katanya. “Mereka orang kita.”
Dari belakang, seseorang masuk.
Langkahnya tegas. Wajahnya serius.
“Bang Kinan.”
Kenanga menghela napas panjang. “Kenapa Bang Kinan bisa di sini?”
Kinan menatapnya tajam, menyapu pandangan ke tubuh Kenanga yang penuh luka. “Menyelamatkan nyawa kamu.”
Kenanga terkekeh. “Kayaknya justru aku yang nyelamatin banyak orang.”
Kinan tidak menanggapi. Ia hanya melirik pria berbaju hitam yang berdiri di samping Kenanga.
“Dia siapa?” tanyanya.
Kenanga ikut menoleh, tapi pemuda itu sudah melangkah mundur, seolah tak ingin ada penjelasan lebih jauh tentang dirinya.
“Seseorang yang kebetulan lewat,” katanya santai.
Kinan menyipitkan mata, tapi memilih tidak bertanya lebih lanjut.
Pemuda itu menatap Kenanga sebentar, lalu berbalik, berjalan pergi begitu saja ke dalam kegelapan.
Kenanga menatap punggungnya, menahan dorongan untuk bertanya lebih banyak.
“Siapa dia sebenarnya…?” gumamnya.
Kinan menghela napas. “Itu yang harus kita cari tahu.”
Kenanga mengepalkan tangan. Apa pun yang terjadi, ini belum berakhir.
*****
Bagaspati melihat ke sekelilingnya dengan panik. Anak buahnya sudah terkapar, para petarung bayaran yang ia percaya bisa menghabisi siapa pun kini tak berdaya di lantai.
Robert tak bergerak, Joe Han merintih kesakitan, dan Masimura tak sadarkan diri.
Bagaspati menggertakkan giginya. “Sial! Kita pergi!”
Tanpa membuang waktu, ia berlari ke pintu belakang gudang, diikuti oleh beberapa pengawalnya yang masih tersisa. Mereka menghilang ke dalam kegelapan malam, meninggalkan tempat itu dalam keadaan porak-poranda.
Kenanga ingin mengejar, tapi Kinan meraih lengannya. “Nggak usah! Kita punya hal yang lebih penting!”
Kenanga menoleh, lalu melihat Puspita dan Reno berdiri di depan sebuah kontainer biru besar.
Puspita mengeluarkan sebuah alat dari sakunya, menempelkan perangkat itu ke gembok elektronik yang mengunci pintu kontainer. Beberapa detik kemudian—
“Klik.”
Gembok terbuka.
Dengan nafas tertahan, mereka membuka pintu kontainer perlahan.
Yang mereka lihat di dalam membuat dada mereka sesak.
Puluhan anak gadis, sebagian besar remaja belasan tahun, berdesakan di dalam. Wajah-wajah ketakutan mereka menyambut cahaya dari luar, mata-mata mereka yang kosong kini mulai menemukan harapan.
Beberapa anak menangis pelan, yang lain menggigil ketakutan.
Reno mengumpat pelan. “Gila… Seberapa lama mereka dikurung di sini?”
Bima, yang selama ini lebih banyak diam, mengepalkan tinjunya keras. “Bangsat mereka! Ini bukan cuma penculikan, ini genosida!”
Kenanga masuk ke dalam kontainer, berjongkok di depan seorang gadis kecil yang memeluk lututnya dengan ketakutan.
“Adik… kita akan membawa kalian pulang,” katanya lembut.
Gadis itu menatap Kenanga dengan mata basah, lalu mengangguk pelan.
Dari kejauhan, suara sirene polisi mulai terdengar.
“Akhirnya mereka datang,” gumam Kinan.
Kenanga berdiri, matanya masih terpaku ke anak-anak itu. “Semoga kali ini mereka benar-benar ada di pihak kita.”
Tidak lama, belasan mobil polisi berhenti dengan cepat. Puluhan personel bersenjata lengkap turun, bergerak cepat ke arah gudang.
Kenanga menghela napas lega. Mereka butuh bantuan untuk mengurus para korban dan membawa mereka ke tempat aman.
Tapi sesuatu terasa aneh.
Polisi-polisi itu tidak langsung menuju ke para korban.
Mereka justru mengepung Kenanga, Kinan, Reno, Puspita, dan Bima.
Kenanga menyipitkan mata. “Bang Kinan… ada yang aneh.”
Belum sempat Kinan menjawab, suara seorang perwira menggelegar.
“KENANGA HANGESTRI! KINAN, RENO, PUSPITA! KALIAN SEMUA DITANGKAP ATAS DUGAAN TERLIBAT JARINGAN PERDAGANGAN MANUSIA!”
“APA?!” Reno hampir meneriakkan kata itu.
Puspita langsung mundur selangkah, waspada. “Sial… Ini jebakan.”
Bima mengepalkan tinjunya. “Gila! Kita yang nyelamatin anak-anak ini!”
Seorang perwira wanita—AKP Sulastri—berjalan ke depan dengan wajah keras. Ia menatap mereka dengan dingin.
“Jangan melawan. Kami punya perintah.”
Kinan menatap Sulastri tajam. “Dari siapa perintah ini, AKP Sulastri?”
Sulastri tidak menjawab, tapi sekilas, matanya tampak menyimpan sesuatu.
Kenanga dan yang lain tidak punya pilihan. Puluhan senjata ditodongkan ke arah mereka.
Dari kejauhan, di atas sebuah gedung yang gelap, pemuda berbaju hitam itu berdiri diam, memperhatikan semua yang terjadi.
Matanya tajam, ekspresinya tetap dingin.
Dia tidak bergerak.
Tidak berusaha menyelamatkan mereka.
Hanya berdiri, menatap, sebelum perlahan menghilang ke dalam kegelapan.
BERSAMBUNG!
*Cerita ini fiksi. Nama, tempat, dan peristiwa hanyalah imajinasi. Jika ada kesamaan, itu kebetulan belaka.
*Naskah ini disusun berdasarkan berbagai sumber terpercaya dengan pengolahan redaksional oleh tim Indonewsia.id. Untuk informasi selengkapnya, silakan merujuk pada tautan sumber berita yang disertakan.