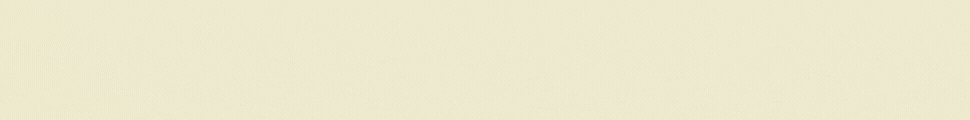Tangannya menggeser senjata kecil di balik jaket. Sorot matanya tak lepas dari bangunan itu. Ia tahu, malam ini darah mungkin tumpah.
Tapi ada satu hal yang lebih penting: memastikan bahwa kebenaran dan kebiadaban tidak lagi memakai jubah yang sama.
***
Aula itu sunyi. Hening seperti makam yang menanti pelayat. Lampu gantung di langit-langit memancarkan cahaya kekuningan yang temaram, melemparkan bayangan panjang ke lantai batu yang dingin dan tak bersahabat.
Suasana menegang. Dingin menusuk tulang, bukan karena suhu, melainkan karena aura kematian yang menggantung.
Kenanga berdiri tegak di tengah ruangan, tubuhnya siaga, napasnya perlahan. Matanya menyapu ruangan—tajam, waspada.
Di hadapannya, lima lelaki melangkah maju dalam formasi setengah lingkaran. Tatapan mereka meremehkan, bibir mereka melengkung dalam senyum congkak yang menantang maut.
“Lihat betina ini,” cibir salah satu, meludahi lantai. “Sok jagoan.”
Yang lain berseru dengan suara lengket seperti lendir, “Ayo, manis. Menyerah saja. Kami tidak ingin meninggalkan bekas di wajah cantikmu.”
Langkah mereka semakin dekat. Lalu—tanpa aba-aba—pukulan pertama meluncur dari sisi kiri. “Rasakan ini, jalang!” Lelaki itu mengayun tangan kasar ke arah pipi Kenanga.
Kenanga bergerak seperti bayangan. Ia memutar tubuh, menghindar sepersekian detik sebelum sikunya menghantam rahang lawannya. Bunyi krek tulang retak menggema singkat. Lelaki itu terhempas ke lantai, menggeliat dalam nyeri, mulutnya mengalir darah.
“Sialan!” pekik yang lain sambil menerjang dengan tendangan lurus ke arah perut. Tapi Kenanga sudah membungkuk rendah, menyapu kaki si penyerang hingga tubuhnya terguling, terbanting keras. Gedebuk!
Tiga lainnya maju bersamaan. Nafas Kenanga terkontrol. Satu lawan banyak bukan hal baru baginya—ini hanya medan lain, dengan dosa yang lebih kental. Pukulan diluncurkan ke arahnya, keras dan brutal, tapi Kenanga menari di antara mereka, tangannya menghajar perut, siku, leher.
Satu lelaki terkapar dengan darah mengalir dari hidung, yang lain terbatuk keras setelah tulang dadanya dihantam lutut.
Keheningan itu kembali. Hanya suara napas dan keluhan luka yang mengisi ruangan.
Lalu, dari bayang-bayang lorong, tiga sosok melangkah perlahan: Rukhman. Jawal. Muntako.
Tak ada senyum di wajah mereka. Tak ada cemooh. Mereka datang sebagai eksekutor, bukan provokator.
“Cukup main-mainnya,” gumam Rukhman, suaranya datar, tajam seperti bayonet. “Sekarang giliran kami.”
Tanpa basa-basi, Rukhman menerjang. Tinju kirinya cepat, mengarah ke wajah. Kenanga menghindar, tetapi dari belakang, Jawal muncul dengan tendangan berputar ke arah rusuk.
Bughh!—kena. Kenanga terlempar setengah langkah, nyeri merayap naik ke lengannya.
Muntako tak membuang waktu. Ia melayang dengan tendangan tinggi. “Mampus kau!” serunya. Kenanga menunduk, nyaris tersabet tumit maut itu.
Tubuhnya berdenyut. Napasnya berat. Tapi pikirannya tetap dingin. Ia mengingat pertarungan melawan pembunuh bayaran Bagaspati—rasa takut tak akan menyelamatkan siapa pun.
Ia balas menyerang. Tinju ke bahu Rukhman—keras dan dalam. Lawan itu terhuyung.
Jawal datang lagi, kakinya menghantam. Tapi Kenanga menangkap pergelangan itu, memutarnya dengan kekuatan penuh—brak!—tubuh Jawal menghantam lantai, bahunya menghantam batu dengan suara yang mengerikan.
Muntako maju, teriakannya liar. “Selesai kau!” Tapi Kenanga menghindar ke kanan, lalu mengayunkan sisi telapak tangan ke tenggorokannya. Lelaki itu mengerang, tercekik, terjatuh sambil memegangi leher.
Rukhman masih berdiri. Luka di pelipisnya berdarah, tapi matanya menyala penuh dendam. Ia melompat maju untuk serangan terakhir.
“Kau akan mati di sini!”
Kenanga berputar cepat, tangannya menghantam pelipis Rukhman dengan kekuatan yang terkumpul dari semua amarah, kehilangan, dan tekadnya.
DUGHH!
Tubuh Rukhman limbung. Lalu jatuh. Tak bergerak.
Semua hening.
Kenanga berdiri di tengah ruangan yang kini penuh tubuh tergeletak. Napasnya berat. Darah di sudut bibirnya. Tapi matanya masih menyala. Tidak sebagai korban. Tapi sebagai ancaman terakhir.
“Siapa selanjutnya?” bisiknya, suara rendah itu bergema di aula batu. Dan tak seorang pun menjawab.
***
Rumah utama pimpinan Al Mubarok terbungkus keheningan yang tak wajar, seperti napas terakhir sebelum ajal tiba.
Lampu gantung tua bergoyang pelan, memantulkan cahaya kekuningan yang menari di dinding batu—seolah roh-roh gentayangan menunggu giliran untuk berbicara.
Kenanga berdiri di ambang pintu yang baru saja didobraknya. Ruangan itu dipenuhi aura kematian.
Di dalam, Hanafi—alias Mustar—berdiri dengan tubuh menegang, pistol di tangannya mengarah pada seorang gadis muda yang menggigil ketakutan di sudut ruangan.
“Siapa kau? Kau pikir bisa membunuhku, hah?” Hanafi mendesis, suaranya menyayat seperti ular. “Aku ini ustaz! Orang yang dihormati!”
Kenanga melangkah masuk, cahaya menyapu wajahnya yang dingin. “Orang suci? Hah.” Ia menyeringai getir. “Kau lebih pantas disebut iblis maksiat yang berselmut ayat-ayat.”
Dari balik bayangan gelap di belakang Hanafi, sosok Halimah perlahan muncul. Wajahnya pias, tapi sorot matanya mengandung bara. “Itu benar, Kenanga…” ucapnya pelan namun jelas. “Dia bukan ustaz. Dia monster.”
*Naskah ini disusun berdasarkan berbagai sumber terpercaya dengan pengolahan redaksional oleh tim Indonewsia.id. Untuk informasi selengkapnya, silakan merujuk pada tautan sumber yang disertakan.