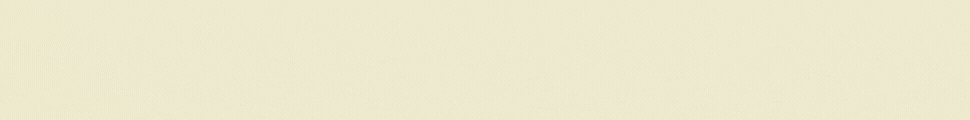Setelah Halimah menyelesaikan kisahnya, ia membawanya keluar dari tempat itu. Langkah mereka tenang, namun di bawah permukaannya, dunia seolah menahan napas.
Di depan sebuah rumah sederhana, pemuda itu menurunkan tubuh Halimah dengan lembut. Jemarinya yang dingin membuka ponsel, mengetik cepat:
“Terima gadis itu. Gali yang perlu. Jangan tanya siapa aku.”
Lalu, ia menghilang ke kegelapan, seperti mimpi buruk yang enggan berpamitan.
***
Kenanga tergagap saat ponselnya bergetar. Sebuah pesan, tanpa nama pengirim, hanya kata-kata pendek yang membuat dadanya menegang. Ia membuka pintu.
Tubuh Halimah tergeletak di sana, basah, gemetar, seperti kutukan yang dikirim malam.
Di ruang tamu, Halimah kini duduk berselimutkan keheningan. Teh panas mengepul, tapi tangannya terlalu dingin untuk merasakannya.
Reno dan Puspita duduk tegang. Kenanga berdiri, matanya menyala seperti bara dalam gelap.
“Apa yang terjadi padamu?” tanyanya tajam, bukan karena tidak peduli, tetapi karena ingin mengerti secepat mungkin.
Halimah mulai bercerita. Tentang perburuan. Tentang lima bayangan. Tentang lompatan ke sungai, dan laki-laki misterius yang menyelamatkannya.
“Bangsat!” Kenanga melempar ponsel ke sofa. Suaranya pecah, tubuhnya bergetar. “Pakai agama untuk nyalurin kebinatangan… Setan-setan itu nggak layak hidup!”
Reno meneguk ludah. Puspita menatap Halimah, syok dan iba bercampur. Tapi tidak ada yang bicara. Mereka tahu, badai baru saja mulai.
Kenanga meraih ponselnya lagi, menekan nomor Kinan.
“Bang Kinan. Dengar. Halimah… dia tahu banyak hal. Dan ini… ini lebih busuk dari yang kita duga. Kita harus bertindak. Sekarang.”
Di seberang sana, suara Kinan terdengar dingin dan pelan. Sebuah nada yang membuat bulu kuduk siapa pun berdiri.
Dan di luar sana, dalam bayangan pohon besar yang mengawasi rumah itu, pemuda berjaket hitam berdiri tak bergerak.
Matanya tajam. Tidak puas. Tidak tenang. Ia tahu Halimah selamat. Tapi keselamatan adalah ilusi. Dan malam ini, terlalu banyak rahasia untuk dibiarkan tetap tertidur.
***
Hanafi Al Mubarok terbangun dengan tubuh menegang, napas tersengal-sengal seolah baru saja keluar dari mimpi yang menjerat lehernya.
Keringat dingin membasahi wajah pucatnya, menetes dari pelipis ke leher, saat pandangannya tertuju pada layar ponsel yang bergetar nyaring di meja.
Nama Bagaspati muncul dengan huruf merah menyala, seperti bara yang membakar dada. Detak jantungnya bergemuruh, irama perang yang membangunkan segala ketakutan.
Ia menarik napas panjang, berusaha menstabilkan tubuh yang gemetar, lalu mengangkat telepon dengan jemari yang dingin.
“Mustar!” suara dari seberang membakar seperti cambuk. “Bangun! Lu pikir lu bisa enak-enakan tidur sama gundik-gundik lu?! Mana Halimah?! Kenapa dia belum sampe?!”
Hanafi, atau nama lamanya—Mustar—terdiam. Ketakutan menelan lidahnya. Ia melirik dua perempuan muda yang kini bangun, tubuh mereka diselimuti kain sutra tipis, mata mereka buram, bingung. Ketegangan di udara membuat malam terasa lebih sempit.
“P—pak… saya akan urus… Sekarang. Cuma kendala kecil. Malam ini… selesai,” katanya lirih, seperti bisikan tikus dalam sarang ular.
“Janji apa?!” hardik Bagaspati, raungannya mengiris udara. “Lu bikin gue turun tangan sendiri, Mustar… gue pastiin lu bakal gue kubur bareng jubah ustaz lu itu!”
Belum sempat Hanafi menjawab, ketukan keras membelah malam.
DUG! DUG! DUG!
Suara panik dari luar pintu: “Pak Ustaz! Ada perempuan… dia nyerang orang-orang kita! Dia… nyari Anda!”
Tubuh Hanafi tegang. Bukan karena takut—tapi karena kemarahan yang menggelegak seperti lava di perut bumi.
“Siapa?” suaranya pelan, nyaris berbisik, namun setajam pisau cukur.
Tidak ada jawaban pasti. Hanya ketukan panik, suara yang bergetar karena rasa takut.
Sementara itu…
Di balik hutan yang membekap padepokan dengan gelapnya, Kenanga menjebol pintu dengan hantaman tunggal.
Suara pintu terhempas menggema, meretakkan kesunyian malam. Matanya membara. Nafasnya berat. Ia tak datang untuk bertanya. Ia datang untuk menghakimi.
Dua lelaki berseragam hitam mencoba menghalangi—satu dihantam tepat di rahang, membuat tubuhnya terpental ke dinding; yang satu lagi dihajar tendangan telak ke dada, jatuh mencium lantai dengan bunyi nyaring tulang yang retak. Mereka tak punya waktu untuk menyesali.
Langkah Kenanga terus maju, gemanya membentur tembok batu padepokan, menciptakan irama yang tak manusiawi—langkah malaikat penghukum.
Matanya menyapu ruangan, mencari wajah yang selama ini bersembunyi di balik jubah dan sabda.
Di luar, di dalam mobil yang terparkir di balik semak-semak, Reno dan Puspita menatap dengan cemas. Halimah duduk di antara mereka, tubuhnya berguncang, wajahnya membeku dalam ketakutan.
Tatapan mereka terarah ke bangunan itu—tempat Kenanga kini bertempur dengan luka-luka masa lalu dan bara dendam yang tak padam.
Dan dari balik bayang-bayang…
Dia.
Pemuda berjaket hitam berdiri di bawah pohon beringin tua, tubuhnya dibalut kegelapan. Matanya tajam, headset kecil tertempel di telinga. Suaranya datar, tanpa emosi:
“Semuanya terkendali. Pantau jalur keluar. Jangan ada celah.”
*Naskah ini disusun berdasarkan berbagai sumber terpercaya dengan pengolahan redaksional oleh tim Indonewsia.id. Untuk informasi selengkapnya, silakan merujuk pada tautan sumber yang disertakan.