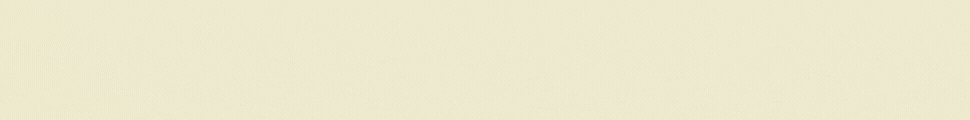“Dan satu hal lagi, AKP Sulastri… Jangan percaya siapa pun. Bahkan bayanganmu sendiri.”
Sulastri keluar dari ruangan dengan langkah berat. Udara di luar seakan lebih dingin dari sebelumnya.
Ia tahu, dunia sedang berubah. Dan ia harus memilih: menjadi pelindung kebenaran, atau menjadi bagian dari kebohongan yang membusuk dari dalam.
***
Lorong menuju ruang tahanan itu lengang. Lampu gantung berkedip pelan seperti nafas terakhir nyala lilin.
Suara sepatu AKP Sulastri memantul di sepanjang dinding lembap yang dipenuhi retakan kecil.
Tangan kirinya menggenggam map, tangan kanannya tak lepas dari gagang pistol di pinggang.
Di ujung lorong, sebuah pintu besi menunggu, hitam dan dingin seperti rahasia yang dikubur dalam-dalam.
Di baliknya, Kenanga, Kinan, dan Bima masih dikurung, menunggu kepastian yang belum juga datang.
Sulastri berhenti sejenak, menarik napas dalam. Bayangan wajah pemuda berjaket hitam tadi melintas lagi di kepalanya, membuat tengkuknya kembali menggigil.
“Siapa kau sebenarnya?” gumamnya lirih, nyaris seperti doa yang putus di ujung lidah.
Pintu terbuka dengan suara decitan panjang.
Kenanga menoleh cepat. Matanya masih menyala seperti bara, tapi sorotnya lebih dingin kini. “Kami dibebaskan?” tanyanya tanpa basa-basi.
“Status kalian tahan rumah,” jawab Sulastri, nadanya datar tapi tegas. “Kalian akan dikawal. Semua aktivitas akan dipantau. Jangan coba main api.”
Bima bangkit perlahan, matanya tajam menatap perwira itu. “Siapa yang menarik tali dalam bayang, Bu Sulastri? Kita sama-sama tahu ini bukan hanya soal Bagaspati.”
Sulastri menatap ketiganya satu per satu. “Kalian bukan anak kecil. Jangan berpura-pura bodoh. Apa pun yang kalian kejar, makin dalam kalian masuk, makin besar yang ingin menelan kalian hidup-hidup.”
Kinan memegang tangan Kenanga, suaranya pelan tapi tegas, “Kami tidak masuk ke dalam. Kami lahir di dalamnya.”
Diam sejenak. Lalu Sulastri menyibak map di tangannya, menarik tiga lembar kertas, tanda pembebasan. Ia menandatangani satu per satu, lalu menyerahkannya.
“Mulai malam ini, kalian bebas… dalam sangkar yang lebih besar,” katanya.
Tiba-tiba, dari arah lorong belakang, terdengar derit logam dan langkah ringan.
Sulastri menoleh cepat. Bayangan seseorang muncul sebentar—sekilas saja—lalu menghilang ke dalam gelap.
Kenanga mendekat. “Siapa itu?”
Sulastri terdiam. “Hanya… bayangan.”
Tapi mereka bertiga tahu, malam ini bukan sekadar tentang kebebasan. Ini awal dari sesuatu yang lebih dalam, lebih berbahaya, dan lebih tak terduga.
Dan di balik jeruji waktu dan kelam lorong, si pemuda berjaket hitam—si bayangan itu—mungkin sedang menyusun langkah berikutnya.
***
Langit mendung menggantung rendah, kelabu dan berat, seolah turut meratap dalam pemakaman yang sunyi. Angin malam berembus pelan, menyeret aroma tanah basah dan bunga kenanga liar yang tumbuh di sudut makam.
Suasana itu seperti beku dalam waktu—hanya bisikan dedaunan dan desau nafas yang terdengar.
Ambar berdiri terpaku di depan sebuah batu nisan sederhana. Tangannya yang keriput menyentuh pelan permukaan dingin marmer putih yang memuat nama suaminya: Irjen Anumerta Satya Negara bin Saka Negara.
Lelaki yang dulu menjadi tiang kekuatan keluarganya kini hanya tinggal nama yang diukir abadi di batu. Gugur dalam tugas. Meninggalkan lubang yang tak mungkin ditambal—bahkan oleh waktu.
Wajah Ambar pucat pasi. Tatapannya kosong, tenggelam dalam kabut Alzheimer yang menggerogoti kenangan, namun malam ini… semuanya terasa terlalu nyata. Terlalu menyakitkan.
“Kenanga… kenapa kau selalu bermain dengan api?” gumamnya pelan, nyaris tak terdengar, seperti bisikan roh kepada malam. “Kenapa harus kau yang memikul bara itu?”
Air mata mengalir perlahan, membasahi pipi tuanya yang telah dihiasi garis-garis usia. Setiap tetes adalah serpihan duka, membentuk luka baru dari kenangan yang lama.
Dari kejauhan, Puspita berjalan mendekat sambil menggenggam payung hitam. Gerimis tipis membasahi bahunya, namun ia tak peduli.
Tatapannya tak lepas dari sosok ibunya yang rapuh di tengah taman makam itu. Ia merasakan guncangan dalam dirinya—antara ingin memeluk, atau membiarkan ibunya larut dalam kehilangan yang hanya bisa dimengerti oleh dua hati yang pernah saling mencinta begitu dalam.
“Bu… sabar ya.” Suaranya lirih, nyaris seperti doa. “Kenanga itu kuat. Percayakan semuanya pada AKP Sulastri. Mereka akan menuntaskan ini.”
Ambar perlahan menoleh. Matanya basah, tatapannya jauh, seperti sedang berbicara pada hantu masa lalu. “Satya… kau didik dia terlalu keras. Kau ingin dia jadi baja. Tapi lihat sekarang… dia terlalu kuat untuk menghindari luka. Dia terbakar… seperti kau.”
Suaranya pecah, bergetar di udara dingin yang enggan bergerak. Kata-katanya seperti pecahan cermin—tajam, berserakan, memantulkan kepedihan yang tak bisa dirapikan.
Puspita merapatkan jaketnya, mencoba menahan dingin yang berasal bukan hanya dari cuaca, tapi dari ketakutan yang perlahan merayap ke jantungnya. “Bu… jangan salahkan Ayah. Kenanga jadi seperti ini bukan karena didikan keras. Tapi karena cinta. Karena tanggung jawab. Dia ingin melindungi kita… bahkan ketika itu menghancurkannya perlahan.”
*Naskah ini disusun berdasarkan berbagai sumber terpercaya dengan pengolahan redaksional oleh tim Indonewsia.id. Untuk informasi selengkapnya, silakan merujuk pada tautan sumber yang disertakan.