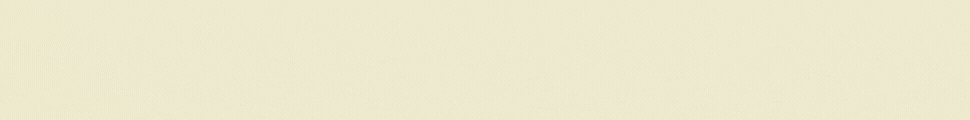JEJAK KENANGA 3: MAKSIAT BERSELIMUT AYAT
Debu dan sarang laba-laba melekat di wajah Halimah, bercampur keringat dan air mata yang mengalir diam-diam. Nafasnya memburu, dada naik-turun tak beraturan.
Dari balik celah papan rumah panggung yang lapuk, matanya mengintai, menanti—atau mungkin ditunggu.
Baca Juga:
Langkah-langkah berat mengitari rumah. Suara sepatu menghantam papan kayu.
“Dia di sini…” suara serak laki-laki tua menyayat kesunyian malam.
“Endus terus,” timpal suara lain, lebih muda, dingin seperti bilah parang yang diseret.
Halimah menahan napas. Luka sobek di pahanya berdetak seperti nadi. Perihnya menusuk, tapi kepalanya tetap dingin.
Ini bukan sekadar pelarian. Ini tentang menjaga sesuatu. Sesuatu yang tak boleh jatuh ke tangan mereka.
Dari atas rumah panggung, suara parau meneriakkan perintah,
“Cari di bawah! Bakar kalau perlu!”
Langkah kaki semakin dekat. Kayu lantai berderit seperti mengaduh. Halimah menyatu dengan bayangan, tubuhnya memeluk tanah.
Tangannya meraba-raba dalam gelap. Lalu… sentuhan dingin. Sebilah pisau berkarat. Ditinggal waktu, dilupakan. Tapi malam ini—dipanggil kembali.
Celah papan menganga. Sepasang mata mengintip—mata yang menyala seperti bara di tengah gelap.
“Ketemu—”
Pisau melesat. Jeritan menggelegar. Tubuh tumbang menghantam tanah.
Empat sosok lainnya terdiam sejenak. Lalu kemarahan. Lalu takut.
Dan di tengah mereka, Halimah berdiri. Napasnya berat. Tubuhnya luka. Tapi matanya… menyala.
“Kalian pikir aku akan menyerah?” suaranya rendah, serak, seperti lolongan dendam.
“Kalian salah.”
Dan malam pun menjadi saksi. Gang-gang sempit berlumur bayangan dan darah. Lima sosok haus darah datang.
Tapi Halimah, dengan luka dan pisau, menari bersama maut. Malam itu, tak ada tempat untuk lemah. Hanya kebencian, dan kehendak untuk bertahan hidup.
***
Lorong markas intel itu sempit, pengap, dengan dinding retak yang seperti menyimpan bisikan.
Lampu temaram menggantung rendah, menggoyang pelan setiap kali angin dari ventilasi mendesis keluar, seolah napas terakhir dari rahasia yang terlalu lama disimpan.
Kenanga berdiri sendiri di depan kaca satu arah. Di baliknya, seorang pria kurus duduk tertunduk di kursi interogasi, tangannya diborgol, napasnya berat.
Matanya sembab, dan bibirnya pecah—tapi bukan karena disiksa. Ini luka dari penyesalan. Atau ketakutan.
“Dia anggota Bagaspati?” suara Bima muncul di belakang, berat dan datar.
Kenanga tak menoleh. “Tidak. Dia hanya kurir. Dan sekarang dia tahu terlalu banyak.”
Kinan mendekat, wajahnya muram. “Kita tidak bisa terus begini. Aku… aku tidak yakin siapa yang bisa kita percaya sekarang.”
Kenanga akhirnya berpaling, menatap kedua temannya. “Percayalah pada naluri kita. Kalau tidak, kita semua akan tenggelam dalam skenario mereka.”
Langkah sepatu terdengar dari ujung lorong. AKP Sulastri muncul lagi—jaket dinasnya rapi, tapi kancing atasnya terbuka. Wajahnya kaku. “Kalian akan dipindahkan malam ini.”
“Dipindahkan?” Bima mendekat, matanya menyipit.
“Ke rumah aman. Lokasi rahasia. Tidak ada komunikasi ke luar. Sampai operasi selesai.”
“Penjara dengan nama lain,” gumam Kenanga. Dia tertawa kecil—pahit, getir. “Sempurna.”
Sulastri menatap Kenanga lama, lalu bicara lirih, “Ini harga untuk keadilan. Kita semua membayarnya.”
Tapi Kenanga tahu. Harga itu tak pernah adil. Kadang, keadilan hanya topeng. Dan di baliknya, wajah-wajah seperti Bagaspati, seperti para perwira berwibawa, seperti… siapa pun yang merasa bisa mainkan hidup orang lain demi kemenangan politik atau strategi.
Ketika mereka bertiga berjalan di lorong gelap itu menuju mobil yang menunggu, hanya satu hal yang menggema di kepala Kenanga:
“Jika mereka pikir kami pion, mereka lupa… pion juga bisa membunuh raja.”
***
Sulastri melangkah mundur dengan berat hati, menyembunyikan keresahan di balik rautnya yang dingin.
Ia tahu, mulai detik ini, permainan berubah arah—dan ia bukan lagi pemain utama di atas papan.
Pemuda berjaket hitam itu berjalan pelan mengitari ruangan, matanya menyapu setiap sudut seolah mencatat segalanya.
Langkahnya hening, tapi setiap gerakannya menciptakan tekanan—seperti seseorang yang membawa badai di balik diamnya.
“Kasus Bagaspati lebih dalam dari yang Anda kira,” ucap pemuda itu, tanpa memandang siapa pun.
Suaranya datar, tak beremosi, tapi menusuk. “Ada simpul-simpul tua yang tak ingin dibuka. Jika kalian gegabah, darah akan membanjiri jalanan. Dan kali ini… bukan hanya darah kriminal.”
Surya Natanegara menatap Sulastri tanpa berkedip. “Dengar dia, Sulastri. Dia bukan siapa-siapa di sini, tapi dia tahu lebih banyak dari siapa pun yang pernah kita temui. Jika dia bilang sesuatu, kau dengar. Jangan lawan arah angin—atau kau akan hancur sebelum sempat melihat peta penuh permainan ini.”
Sulastri mengangguk perlahan, meski pikirannya berkecamuk. Ia adalah perempuan yang tumbuh di tengah kecurigaan dan kehati-hatian.
Tapi malam itu, intuisi lamanya berteriak—pemuda itu bukan hanya saksi, bukan juga sekutu. Ia adalah sesuatu yang lain.
Sebelum Sulastri beranjak keluar, pemuda itu berbicara sekali lagi, suaranya serupa desisan ular.