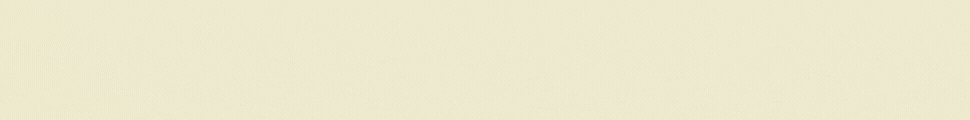Layangan koang bukan sekadar permainan, tetapi simbol warisan budaya Betawi yang masih bertahan di langit Jakarta hingga kini. Suaranya yang khas — koang… koaang… — menjadi nyanyian angin yang menghidupkan sore hari, ketika anak-anak orang dewasa menatap langit penuh warna di atas perkampungan mereka.
Bagi masyarakat Betawi, dahulu layangan koang bukan hanya bentuk hiburan, melainkan bagian dari tradisi turun-temurun yang mencerminkan kreativitas dan kearifan lokal. Di setiap benangnya tersimpan sejarah panjang tentang cara warga kota berinteraksi dengan alam, angin, dan waktu. Dalam sebuah cerita rakyat diceritakan di kawasan Cibubur hingga Kranggan misalnya, layangan ini dimainkan juga dengan ritual ‘bakar menyan’ sebelum diterbangkan saat musim kemarau.
Budayawan dan sastrawan Betawi Yahya Andi Saputra menjelaskan, layangan ini memang terbilang tua, dan sudah dikenal sejak awal abad ke-17 tercatat dalam manuskrip Shohibul Hikayat Syahrodjat, yang menyinggung kemunculannya di kawasan Tanah Abang hingga Gambir.
“Ya sekitar tahun 1800 semua sudah mengenal layangan. Masyarakat Betawi lama, khususnya di wilayah tengah, gemar membuat layangan dengan bentuk busur melengkung. Dari situ muncul bunyi khas saat diterbangkan koang… koang…yang kemudian menjadi namanya atau onomatope,” ujar Yahya saat berbincang-bincang dengan redaksi beberapa waktu lalu.
Ciri utama layangan koang terletak pada bagian atasnya yang disebut gebang. Dahulu, gebang dibuat dari daun gebang, sejenis palma yang banyak tumbuh di Jakarta bagian tengah. Namun kini, karena daun gebang semakin sulit ditemukan, pembuat layangan menggantinya dengan daun kelapa atau lembaran kaca film dalam era kekinian.
Kendati bahan berubah, bentuk busurnya tetap sama: melengkung seperti bulan sabit bertumpuk dengan senderingan di tengah yang menghasilkan dengungan khas.
Nama “koang” sendiri berasal dari onomatope bunyi alami. Seperti kata kukuruyuk meniru suara ayam, maka “koang” meniru dengungan layangan yang menembus angin.
“Koang… koang… begitulah suara itu terdengar di langit Betawi, dan dari sanalah lahir namanya,” terang Yahya Andi Saputra.
Seiring waktu, layangan koang berkembang menjadi beberapa jenis dengan fungsi dan ciri khas masing-masing:
Koang Hias, dirancang agar tampak indah dan menarik dengan warna cerah dan pola khas Betawi, biasa tampil dalam festival budaya.
Koang Aduan (Laga), dikenal juga sebagai “koang j-bros”, dibuat khusus untuk diadu di udara.
Koang Variasi Ekor Pendek, memiliki ekor pendek untuk menambah kestabilan dan kecepatan saat bermanuver.
Koang Pengeluar Suara (Koang Asli), bentuk klasik dengan struktur busur ganda yang menimbulkan dengungan khas — diyakini sebagai cikal bakal layangan Betawi dalam manuskrip kuno.
Warisan Angin Betawi
Menurut Yahya, layangan koang sudah termasuk dalam kategori Warisan Budaya Takbenda (WBTb) Betawi, meski belum resmi didaftarkan.
“Masih perlu kajian dan penetapan maestro, tapi jelas layangan ini sudah diwariskan secara turun-temurun. Di tempat saya, Cilandak, juga banyak yang bisa bikin,” ujarnya.
Kini, meski layangan hias modern banyak dijual di sepanjang Jalan Raya Bogor hingga Cisalak, layangan koang tetap hidup di tangan para pengrajin tradisional di Pal Merah dan Rawabelong, terutama di toko legendaris yakni, Koang Kelabang Rawabelong. Mereka tetap setia membuatnya dari bambu tipis, tali kapas, dan lembaran alami menjaga nyanyian angin agar tak hilang dari langit Jakarta.