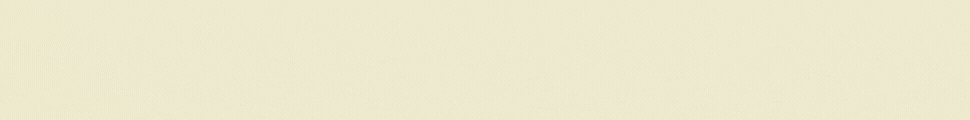JEJAK KENANGA 1: PEREMPUAN DI UJUNG BARA
Ruangan itu luas. Cahaya dari puluhan layar memantul ke wajah perempuan yang duduk di tengah. Kenanga Hangestri. Matanya tajam, membaca laporan yang terpampang di hadapannya.
Suasana rapat hening, hanya suara ketikan jemari Puspita, ajudannya, yang terdengar.
“Ibu Presiden, waktu Anda hanya sepuluh menit lagi sebelum konferensi pers.”
Kenanga mengangkat wajahnya dari laporan yang terpampang di layar tablet. Puluhan layar di hadapannya menampilkan wajah-wajah para gubernur dari seluruh Indonesia.
Cahaya putih dari ruangan itu memantul di matanya yang tajam.
Di sekelilingnya, ajudan dan staf bekerja dalam senyap, menunggu instruksi. Reno, penasihat kepercayaannya, berbicara dengan nada optimis.
“Persepsi publik baik, Bu,” katanya. “Survei menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat cukup tinggi atas kebijakan Anda.”
Kenanga menatapnya sebentar, lalu meletakkan tabletnya.
“Saya tidak peduli survei,” potongnya, suaranya dingin. “Kita belum melakukan apa-apa.”
Puspita, ajudannya, mencatat cepat. Para gubernur di layar menanti instruksi selanjutnya.
“Arahan untuk kepala daerah, Bu?” tanya salah satu dari mereka.
Kenanga menyandarkan tubuhnya, menghela napas perlahan. “Kita turun ke lapangan.”
“Kenanga! Bangun! Udah hampir pagi!”
Cahaya ruangan besar lenyap. Puluhan layar itu hilang.
Matanya terbuka. Nafasnya berat. Sial. Mimpi lagi.
Di ambang pintu, Ambar, ibunya, berdiri dengan senyum tipis. “Nanti telat ke sekolah.”
Kenanga masih diam beberapa detik, lalu akhirnya bangkit, mengusir sisa mimpi yang mengganggu pikirannya.
“Iya, Bu.”
Di sekolah, Kenanga duduk diam, matanya menerawang ke luar jendela. Reno datang dari belakang, menjatuhkan diri ke kursi dengan santai.
“Kenapa muka kayak habis lihat hantu?” tanyanya, menyenggol bahu Kenanga.
“Bukan hantu.” Kenanga menghela napas. “Mimpi.”
“Mimpi apa?”
Kenanga ragu sebentar, lalu akhirnya berkata, “Gue lihat diri gue… jadi presiden.”
Reno menatapnya dua detik sebelum tertawa keras. “Hahaha! Ken, itu tandanya lu memang ditakdirkan buat sesuatu yang besar!”
Kenanga menggeleng, tersenyum tipis. “Mimpi bukan takdir. Gue cuma anak biasa.”
Reno mendengus. “Anak biasa yang nggak bisa diam lihat ketidakadilan.”
Kenanga terdiam. Reno benar.
*****
“Aku ingin tahu, apa yang bisa kulakukan?”
Kinan Arundhati meletakkan cangkir kopinya. “Lurus banget anak ini. Biasanya orang bertanya, ‘Benarkah ini?’ atau ‘Siapa yang membocorkan?’”
“Aku nggak peduli siapa yang bocorin,” Kenanga menatapnya tajam. “Yang kupedulikan adalah gimana kita bisa lawan mereka.”
Kinan terkekeh. “Korupsi di negeri ini kayak jamur di musim hujan. Dicabut satu, tumbuh sepuluh.”
“Apa lantas kita harus diam?”
“Aku suka semangatmu, Nak. Tapi melawan sistem bukan sekadar soal niat. Kamu punya bukti? Strategi? Jaringan?”
Kenanga terdiam. Ia tak punya semua itu.
Kinan menghela napas, lalu menyodorkan kartu namanya. “Datang ke kantor besok. Ada banyak yang harus kau pelajari.”
Kenanga menatap kartu itu. Hanya selembar plastik tipis, tapi ia tahu, ini bisa jadi awal segalanya.
*****
“Gue ngerasa ada yang aneh sama Guntur,” Kenanga melipat tangannya, menatap Reno yang sibuk mengunyah bakwan di kantin sekolah.
“Hah? Aneh gimana? Jangan-jangan lu naksir?” Reno cekikikan.
“Serius, No. Gue pernah lihat dia masuk ke mobil hitam, sopirnya bukan orang sembarangan. Dan kemarin, gue lihat dia nyerahin sesuatu ke anak kelas sebelah. Wajahnya tegang.”
Reno mengerutkan dahi. “Lu yakin itu narkoba? Bisa aja dia jualan skincare.”
Kenanga mendengus. “Gue butuh bukti. Kita harus cari tahu.”
Reno mendesah, lalu menatap Kenanga penuh keraguan. “Oke, tapi kalau ini ketahuan, kita bisa celaka, Ken.”
“Justru karena itu kita harus berhati-hati.”
Mereka menguntit Guntur ke sebuah gudang tua di pinggiran Jakarta. Dari balik bayangan, mereka melihat transaksi mencurigakan—paket-paket kecil berpindah tangan.
“Gila… ini beneran bandar narkoba, Ken,” bisik Reno.
“Itu dia bosnya,” Kenanga menunjuk pria gempal berkepala plontos.
“Namanya Herman. Dulu dia anak buah Bagaspati, sekarang dia ngelola bisnis sendiri,” suara seseorang menyusup di belakang mereka.
Kenanga dan Reno refleks berbalik. Seorang pria dengan jaket kulit berdiri di sana.
“Santai, gue dari IndependenNews. Nama gue Bima,” katanya sambil menyeringai. “Bang Kinan kirim gue ke sini. Kayaknya lu berdua cari gara-gara yang sama.”
Kenanga menyipitkan mata. “Kinan? Oya bang Kinan wartawan itu?”
“Iya. Dia dapet info kalau ada jaringan baru yang melibatkan anak sekolahan. Nah, sekarang kita punya saksi,” Bima menatap Reno dan Kenanga.
“Dan… kita harus cari bukti lebih kuat,” Kenanga menambahkan.
“Atau kita lapor polisi aja sekarang?” usul Reno dengan wajah tegang.
“Belum cukup. Kita butuh lebih dari sekadar laporan. Kita butuh rekaman, transaksi langsung, atau… sesuatu yang lebih besar,” Kenanga berpikir keras.
Mereka menyelinap lagi ke gudang. Tapi kali ini mereka ketahuan.
“SIAPA KALIAN?!”
Tiga pria bertubuh kekar menyerbu. Reno panik, tapi Kenanga sigap.
Satu pukulan melayang ke arahnya, Kenanga menangkis, lalu memutar tubuhnya cepat—kakinya menendang perut lawan pertama hingga tersungkur.
Lawan kedua mengayunkan pisau. Kenanga melompat ke belakang, lalu menyambar kayu di dekatnya. Ia menghindari serangan, lalu menghantam tulang kering pria itu dengan brutal. Pria itu menjerit dan jatuh.
Lawan ketiga, yang berbadan lebih besar, maju dengan pukulan berat. Kenanga menghindar, lalu menyapu kaki lawan dengan tendangan rendah. Pria itu terjungkal, tapi segera bangkit.
“Lu pikir gampang?” pria itu meludahkan darah, lalu mencabut belati dari ikat pinggangnya.
Kenanga merunduk, fokus. Begitu pria itu menyerang, ia menangkap pergelangan tangannya, memelintirnya dengan cepat—belati jatuh, dan Kenanga memukul ulu hati lawannya dengan siku.
Brak!
Pria itu ambruk, tak sadarkan diri.
Sementara itu, Reno bersembunyi di balik tumpukan kayu. “Kenapa gue ikut ini sih…” gumamnya ketakutan.
Saat keadaan reda, suara sirene polisi menggema di kejauhan.
“Bagus, lu dapet semuanya, kan?” tanya Kenanga ke Bima yang merekam dengan kamera kecilnya.
“Jelas. Ini bakal jadi berita besar.”
Polisi menyerbu, menangkap Herman dan anak buahnya.
Di berita esok harinya, IndependenNews menjadi headline:
“BANDAR BESAR ATAU KELAS TERI? POLISI TANGKAP JARINGAN NARKOBA, NAMUN OTORITAS DITANTANG BONGKAR DALANG SEBENARNYA!”
*****
Nama Kenanga mulai dibicarakan.
Beberapa hari kemudian, Kenanga berjalan di mal bersama Reno.
“Gila ya, kita sekarang terkenal,” kata Reno sambil menyantap es krim.
Kenanga tersenyum tipis. Tapi senyumnya lenyap saat matanya menangkap sosok familiar di kejauhan.
Herman.
Berjalan santai, mengenakan pakaian mahal, dengan dua pria berbadan kekar mengawalnya.
Dia bebas.
Kenanga mengepalkan tangan.
“Anjing,” gumamnya.
Reno menoleh. “Kenapa lu tiba-tiba tegang gitu?”
“Herman.”
Reno menoleh, wajahnya langsung pucat. “Gimana bisa?!”
Kenanga tak menjawab. Tangannya langsung merogoh ponsel dan menekan nomor yang ia hapal di luar kepala.
Kinan.
“Halo?” suara Kinan terdengar di ujung sana.
“Herman masih bebas.”
Hening sejenak.
Lalu suara Kinan terdengar dingin. “Ikuti dia. Jangan sampai dia lepas.”
Kenanga menutup ponsel, matanya penuh tekad.
“Reno, ayo jalan. Gue nggak akan tinggal diam.”
Reno menelan ludah. “Anjir, gue udah nyium bau masalah gede…”
Kenanga berjalan cepat, ponsel masih di telinganya.
“Bang Kinan, denger gak? Aku baru aja liat Herman di sini. Dia masih bebas! Ini gak masuk akal!” suaranya meninggi, emosi meluap.
“Ken, jangan gegabah. Jangan bertindak sendiri—” suara Kinan terputus.
Brak!
Kenanga menghantam dada seseorang. Kuat. Keras. Seperti nabrak dinding hidup. Ponselnya hampir jatuh.
“Sial!” Kenanga mundur selangkah, menatap pria itu dengan tatapan tajam.
Pria itu tinggi, atletis, mengenakan jaket hitam dengan hoodie setengah terangkat. Rahangnya tegas, sorot matanya dingin, seperti seseorang yang selalu waspada.
“Mata lo di mana, Bang?” bentak Kenanga.
Pria itu tak menjawab. Cuma menatapnya, lalu tangannya bergerak cepat—menepuk bahu Kenanga dengan cara aneh. Dua ketukan cepat, satu ketukan pelan.
Insting Kenanga menendang. Sesuatu gak beres. Tapi sebelum dia bisa bereaksi lebih jauh, pria itu bergerak duluan.
DOR!
Sebuah suara pelan, hampir tak terdengar. Seperti suara botol yang pecah di kejauhan.
Telinga Kenanga menangkap suara itu. Tembakan senapan peredam.
“Turun.” Pria itu berbisik tajam, lalu menariknya ke belakang sebuah pilar beton.
Detik berikutnya, sesuatu menghantam dinding di tempat Kenanga berdiri tadi. Pecahan beton berhamburan. Kenanga terkesiap. Itu bukan kebetulan. Itu bidikan mematikan.
Jantungnya berdebar. Pria ini… dia barusan menyelamatkan nyawanya.
Kenanga menatapnya, masih setengah siap menyerang. “Siapa lo?”
Pria itu tetap dingin tak menjawab.
Lalu dia berbalik, berjalan menjauh seolah tak terjadi apa-apa.
Kenanga masih menelan napas, pikirannya berpacu. Si Herman brengsek itu ternyata sudah pasang orang buat menghabisinya.
Dia menoleh ke arah pria tadi. Masih di sana. Berdiri di bayangan, mengawasinya.
Mata mereka bertemu. Lalu pria itu mengangkat tangannya, memberi isyarat seperti mengetik di udara.
Kenanga mengernyit. “Cek ponsel lo,” suara pria itu terdengar pelan.
Kenanga buru-buru melihat ponselnya. Ada satu pesan tak dikenal masuk.
“Pergi dari sini. Mereka belum selesai memburumu. Kita akan bertemu lagi, Kenanga.”
Nafasnya tercekat.
Siapa dia?
Lalu Kenanga menoleh ke arah pria itu.
Kosong.
Dia sudah hilang di antara bayangan malam.
BERSAMBUNG!
*Cerita ini fiksi. Nama, tempat, dan peristiwa hanyalah imajinasi. Jika ada kesamaan, itu kebetulan belaka.
*Naskah ini disusun berdasarkan berbagai sumber terpercaya dengan pengolahan redaksional oleh tim Indonewsia.id. Untuk informasi selengkapnya, silakan merujuk pada tautan sumber berita yang disertakan.