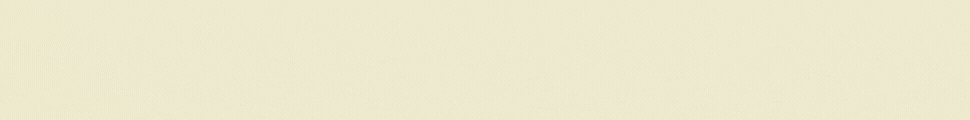INDONEWSIA.ID – Dataran tinggi Gayo dikenal luas sebagai sentra Kopi Gayo, salah satu kopi Arabika unggulan Indonesia yang tumbuh dari sejarah panjang dan dikelola oleh petani kecil.
Namun, wilayah yang sama kini juga menghadapi tantangan krisis ekologi serius lantaran ekspansi lahan sawit dan kerusakan serius akibat banjir bandang dan longsor baru-baru ini yang melanda sejumlah kawasan, di Aceh menjadi tanda tanya besar bagaimana keberlanjutan Kopi Gayo kedepan.
Kopi Gayo ini tidak lahir sebagai tradisi lama masyarakat Aceh. Catatan orientalis Belanda C. Snouck Hurgronje pada akhir abad ke-19 menyebutkan bahwa kopi belum menjadi minuman harian masyarakat. Minuman yang umum kala itu adalah air putih dan air tebu. Kopi masih menjadi barang mahal dan terbatas
Perubahan terjadi pada awal abad ke-20. Setelah perdagangan lada Aceh merosot akibat konflik berkepanjangan, pemerintah kolonial Belanda mulai mengembangkan kopi sebagai komoditas baru. Pada 1908, kopi Arabika diperkenalkan dan ditanam di dataran tinggi Gayo, wilayah yang dinilai memiliki kondisi alam ideal, khususnya di sekitar Takengon dan Danau Lut Tawar.
Sejak saat itu, kebun-kebun kopi berkembang pesat. Pada awal 1930-an, luas kebun kopi di Gayo tercatat mencapai sekitar 13.000 hektare. Kopi Gayo diproduksi untuk ekspor, sementara masyarakat lokal lebih banyak mengonsumsi kopi Robusta dari wilayah lain.
Setelah Indonesia merdeka dan pengakuan kedaulatan melalui Perjanjian Meja Bundar pada 1949, Belanda meninggalkan seluruh aset perkebunan kopi di Gayo. Berbeda dengan di Pulau Jawa, kebun-kebun kopi di Gayo tidak dilanjutkan sebagai perkebunan besar.
Pemerintah Republik Indonesia menyerahkan kebun kopi peninggalan Belanda kepada Ilyas Leubee, perwira asal Gayo yang terlibat dalam perjuangan kemerdekaan. Kebun tersebut kemudian dibagikan kepada masyarakat sekitar, terutama para pekerja kebun. Sejak itulah Kopi Gayo berkembang sebagai usaha rakyat.
Masyarakat yang tidak memperoleh lahan membuka kebun kopi di lahan-lahan kosong. Kini, wilayah Aceh Tengah, Bener Meriah, dan Gayo Lues memiliki sekitar 90.000 hektare kebun kopi Arabika yang sebagian besar dikelola petani kecil dengan kepemilikan lahan rata-rata di bawah dua hektare. Struktur ini menjadikan Kopi Gayo sebagai komoditas pro-rakyat.
Tapi sayangnya, di pasar internasional, Kopi Gayo dikenal sebagai kopi berkualitas tinggi. Namun, pengakuan tersebut sempat diiringi ironi ketika nama “Gayo” tercatat sebagai merek dagang di luar negeri atas nama perusahaan asing. Kondisi itu mendorong upaya perlindungan melalui indikasi geografis agar nama Kopi Gayo tetap menjadi milik daerah dan petaninya.
Kini, tantangan baru muncul. Banjir bandang dan longsor yang melanda sebagian wilayah dataran tinggi Gayo, termasuk Bener Meriah, tidak hanya mengancam permukiman warga, tetapi juga kebun-kebun kopi rakyat yang menjadi sumber penghidupan utama. Curah hujan tinggi dan kerusakan lingkungan meningkatkan risiko bencana di kawasan yang selama ini menopang ekonomi kopi Aceh.
Sejarah Kopi Gayo menunjukkan bahwa kopi ini tumbuh dari pilihan rakyat dan kerja petani kecil. Namun, keberlanjutan Kopi Gayo ke depan juga sangat bergantung pada upaya menjaga lingkungan dataran tinggi Gayo agar tetap lestari dan aman dari bencana.