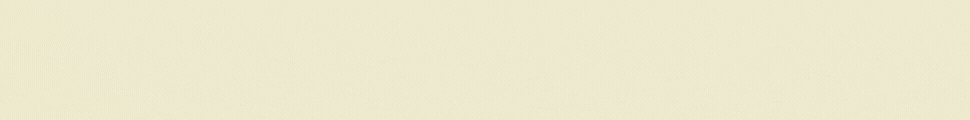JEJAK KENANGA 5: LIMA LELAKI BERTOPENG
Detik jam terdengar nyaring, berdetak di lorong rumah sakit yang hening seperti nisan.
Pukul 02.13 dini hari. Kota terbenam dalam kelam yang nyaris sempurna.
Langit tanpa bintang, jendela berkabut, dan lampu jalan di luar berkedip malas seperti nyawa yang enggan bertahan.
Di sudut ruang tunggu, dua sosok duduk kaku.
Puspita. Reno.
Mata mereka terpaku pada satu titik—pintu kamar perawatan 306.
Tempat di mana Ambar, ibu Kenanga, seharusnya terbaring dalam tidur panjang yang rawan dan rapuh.
Tak ada yang bicara. Keheningan menebal, menggantung seperti tali.
Lalu, bayangan datang.
Lima lelaki bertopeng muncul dari gelap.
Tanpa suara. Tanpa langkah.
Gerakan mereka seperti angin malam—cepat, presisi, berbahaya. Dalam hitungan detik, mereka sudah mengepung Puspita dan Reno.
Tak ada aba-aba. Tak ada kompromi.
DOR!
Tembakan senapan listrik menghantam Reno.
Tubuhnya tersentak, lalu rubuh. Senyap.
Puspita bangkit dengan panik, tapi satu tangan kasar lebih cepat—menarik, membanting, menghantamkan kepalanya ke meja kecil.
Sebuah erangan. Lalu sunyi.
Lelaki-lelaki itu tidak berhenti.
Mereka meluncur ke ruang kontrol keamanan, mengunci dua petugas dengan pukulan senyap.
Satu dari mereka—datar, tanpa emosi—mengendalikan sistem rumah sakit.
Satu gesekan di layar.
CCTV mati. Alarm darurat dibisukan. Komunikasi terputus.
Dalam satu kedipan, rumah sakit berubah menjadi makam bisu.
Misi mereka hanya satu: Ambar.
Langkah mereka menuju kamar 306 nyaris tak meninggalkan jejak.
Pintu dibuka pelan, suara engsel tertahan.
Cahaya temaram menyoroti ranjang. Sosok wanita tua terbaring, tubuhnya rapuh, terhubung infus.
Lelaki bertopeng ketiga maju. Di tangannya—sebuah suntikan kecil, cairan tak bernama mengendap di dalamnya.
Ia membungkuk, mendekati selang infus. Tangannya tenang. Tanpa ragu.
Tapi sesuatu menahan mereka.
Lelaki di depan memberi isyarat—angkat tangan, mata menyipit.
Ada yang tidak beres.
Dan saat mereka menoleh ke ranjang…
Mata yang seharusnya terpejam, terbuka. Penuh nyala.
Itu bukan Ambar.
Itu Kenanga.
Tubuhnya melesat, satu gerakan tajam.
Pisau bedah di meja diayunkan, mencabik lengan lelaki terdekat.
Darah muncrat—hangat, merah, membasahi dinding putih.
Kekacauan dimulai.
Satu lelaki bertopeng menarik pistol—terlambat.
Kenanga meloncat dari ranjang, kakinya menghantam dada pria itu, menjatuhkannya.
Alarm manual meraung.
Langkah-langkah mendekat dari kejauhan.
Mereka kehabisan waktu.
Lelaki ketiga menyerang—kesalahan fatal.
Kenanga menangkap gerakannya, memelintir pergelangan, membantingnya keras ke lantai.
Sebuah pistol terlepas, menghantam lantai—DOR!—peluru nyasar menembus dinding.
Lampu darurat menyala. Merah. Menyiram ruangan seperti peringatan akhir dunia.
Kenanga berdiri tegak. Napas memburu.
Matanya menyala, bukan karena takut—tapi amarah yang membakar dingin.
Para lelaki bertopeng mundur. Terpukul.
Mereka tahu: mereka kalah. Misi gagal.
Dalam panik, mereka kabur.
Meninggalkan tubuh Reno yang tak bergerak.
Puspita yang terkulai.
Dan jejak darah yang menceritakan lebih banyak dari seribu laporan.
Kenanga mengepalkan tangan.
Mereka mengincar ibunya.
Dan malam itu, ia bersumpah dalam diam:
Tak akan ada lagi yang menyentuh Ambar—tanpa harus menebusnya dengan nyawa.
*
Lampu jalan menyusup lewat kaca jendela, memantul di lantai kusam ruang interogasi. Waktu merambat lambat. Tak ada suara selain detik jam tua di dinding.
Dua orang duduk berhadapan.
Satu perempuan. Satunya lagi laki-laki.
AKP Sulastri tidak banyak bicara. Matanya menatap tajam, menusuk ke balik daging, mencari kebenaran yang bersembunyi di balik wajah letih anak buahnya.
Andrian tampak tegang.
Tangan kirinya menggenggam, nyaris tak sadar. Dingin meja baja menembus telapak. Keringat tipis menyusup di pelipis, tapi ia tetap diam. Matanya menghindar.
“Kau tahu kenapa kau di sini,” kata Sulastri.
Pelan. Datar. Tak perlu ancaman.
Andrian tak menjawab. Napasnya berat, tapi tertahan. Kursinya berderit halus ketika ia bergeser sedikit, gugup.
“Telepon itu. Kau angkat.”
Nada Sulastri mengeras.
“Seseorang menyuruhmu membunuh saksi kunci kasus Kurnia Praja. Siapa dia?”
Masih tak ada suara.
Hening seperti kematian.
Sulastri mengangkat tangannya. Sekejap. Telapak tangannya menghantam meja. Suara besi menggema—pendek, tapi cukup memecah nyali.
“Jawab, Andrian. Ini soal nyawa manusia.”
Andrian terkejut. Matanya berkedip cepat. Tapi mulutnya tetap terkunci.
Sulastri menghela napas. Ia duduk kembali, lebih dekat.
“Kau takut.”
Matanya dingin, tapi nadanya turun.
“Tapi aku tahu kau bukan pengecut.”
Diam.
“Dengarkan baik-baik.”
Suara Sulastri berubah jadi bisikan yang menggigit.
“Kalau kau terus diam… aku tidak bisa jamin keluargamu tetap aman.”
Andrian mengangkat wajahnya.
Pucat.
Bibirnya bergetar. Suaranya hampir tak terdengar.
“Kau… tak akan menyentuh mereka, bukan?”
Sulastri tak menjawab. Ia hanya menatap, dalam dan keras. Lalu perlahan bersandar.
“Aku tidak akan.”
“Tapi mereka sudah dalam bahaya, Andrian.”
“Dan satu-satunya yang bisa menghentikan ini… adalah kau.”
Sunyi lagi.
Andrian memejamkan mata. Lama. Lalu tangannya bergerak ke saku jas. Pelan.
Satu benda kecil dikeluarkan—sebuah flash drive. Ia letakkan di atas meja, nyaris tanpa suara.
“Aku merekamnya,” bisiknya.
“Waktu mereka menelepon. Aku tahu aku akan dibuang cepat atau lambat.”
Sulastri mengambil flash drive itu.
Diperhatikannya sejenak.
Kemudian pandangannya kembali tertuju pada Andrian.
“Siapa?” tanyanya.
Satu kata. Berat seperti vonis.
Andrian menelan ludah. Bibirnya gemetar. Tapi ia bicara.
“Orang dalam pemerintahan.”
“Orang dekat Kurnia Praja.”
Sulastri diam.
Sorot matanya tidak berubah. Tapi di dalamnya, sesuatu bergeser.
Ini… lebih dalam dari yang ia duga.
**
Suara beep lembut dari patient monitor mengisi ruangan, bersahut-sahutan dengan desiran samar dari alat bantu pernapasan. Di balik tirai putih tipis, tubuh Ambar terbaring tak bergerak.
Wajahnya pucat, dibingkai rambut yang kini kusut dan lemah. Tabung infus tergantung, dan selang-selang medis menyatu dengan tubuhnya, seolah berusaha mempertahankan sisa-sisa hidup yang nyaris direnggut malam itu.
Kenanga berdiri di sisi ranjang. Tubuhnya diam, tapi matanya penuh badai. Reno duduk tak jauh, bersandar lemah pada kursi dengan bekas luka merah samar di lehernya.
Puspita bersandar pada dinding, lengan menyilang, tatapannya terpaku pada lantai—berusaha mengatur napas, menenangkan gemetar yang belum sepenuhnya hilang.
Tak ada yang bicara. Sunyi menggantung seperti awan hitam sebelum hujan.
Kenanga memecahnya. Suaranya pelan, nyaris tanpa emosi.
“Mereka masuk ke sini… dengan maksud membunuh seseorang yang tak bisa bergerak, bahkan tak bisa membuka mata.”
Reno melirik, wajahnya masih letih. “Kau yakin itu Bagaspati?”
“Siapa lagi yang punya cukup kuasa untuk mengatur lima orang profesional, menonaktifkan sistem rumah sakit, dan tahu posisi tepat kamar ibu?”
Puspita menarik napas. “Kalau benar Bagaspati, berarti ini bukan sekadar sisa dari kasus Kurnia Praja. Ini… sesuatu yang lebih besar.”
Kenanga menatap ibunya, matanya tak berkedip. “Ada sesuatu yang disimpan ibu. Sesuatu yang membuat mereka takut kalau dia bangun.”
Langkah kaki mendekat. Pintu terbuka.
dr. Indrayana masuk. Wajahnya lelah, tetapi gerakannya tetap mantap. Ia memandang mereka satu per satu sebelum akhirnya bicara.
“Saya harus minta kalian keluar dari ruangan ini. Kami perlu menstabilkan kondisi Bu Ambar. Pemantauan akan lebih intensif mulai sekarang.”
Kenanga berbalik cepat. “Dia stabil, kan?”
“Untuk sementara. Tapi tekanan darahnya fluktuatif. Trauma neurologisnya cukup berat. Kami tidak tahu dampaknya saat dia sadar nanti—jika dia sadar.”
Puspita menunduk. Reno memejamkan mata. Kenanga tidak bereaksi.
“Baik,” katanya akhirnya.
Mereka bertiga meninggalkan ruangan perlahan, seolah ada bagian dari diri mereka yang tertinggal di dalam. Kenanga menatap ibunya sekali lagi sebelum pintu tertutup di belakangnya.
Ruang kerja dr. Indrayana tak terlalu besar, tapi rapi. Tumpukan berkas medis tertata di rak, aroma disinfektan bercampur dengan wangi kopi basi di udara. Lampu gantung redup menerangi meja kayu yang penuh coretan.
“Yang terjadi semalam bukan sekadar penyerangan biasa,” ujar dr. Indrayana, duduk di balik mejanya. “Mereka menarget Ambar secara langsung. Dan sistem rumah sakit kami… benar-benar dijebol dari dalam.”
Reno mengerutkan alis. “Orang dalam?”
Indrayana mengangguk pelan. “Kemungkinan besar. Tidak ada polisi yang datang meski alarm darurat sempat aktif. Komunikasi rumah sakit dibungkam sepenuhnya selama dua jam.”
Kenanga bersandar di kursinya. Rahangnya mengeras.
“Mereka mau pastikan tidak ada yang menyentuh saksi terakhir dari kasus itu. Kalau perlu, mereka buat ibuku jadi mayat tanpa suara.”
Puspita menatapnya lekat-lekat. “Apa rencanamu?”
“Aku akan membuat mereka bicara.” Suara Kenanga datar, nyaris dingin. “Satu per satu. Tak peduli seberapa tinggi mereka berdiri atau seberapa dalam mereka sembunyi.”
Indrayana menyilangkan jari di atas meja. “Kalau kau ingin menempuh jalan ini, lakukan dengan kepala dingin. Bukan sebagai anak yang ingin membalas. Tapi sebagai orang yang tahu apa artinya kebenaran.”
Kenanga berdiri perlahan, wajahnya bayangan dari tekad yang bulat.
“Aku tidak akan bertindak gegabah.”
Ia menatap lurus ke depan, matanya menyalak.
“Tapi aku juga tidak akan tinggal diam.”
Tak ada yang menahannya saat ia melangkah keluar. Reno dan Puspita menyusul di belakang. Langkah mereka senyap, tapi berat. Malam ini telah memberi mereka pesan yang jelas:
Ini bukan sekadar perburuan.
Ini permulaan.
Dan Kenanga… akan membalas.
***
Langit malam terhampar kelam di atas kompleks peristirahatan dinas perwira tinggi Kepolisian Republik. Lampu jalan redup, seolah tahu ada kejahatan yang lebih baik tidak disaksikan.
Angin bergerak pelan di antara pepohonan, membawa aroma tanah basah dan kabut tipis yang menggantung di udara.
Di dalam rumah dinas itu, Ambar terbangun dari tidurnya—tapi ini bukan terbangun biasa. Di dalam pikirannya yang limbung, di antara kesadaran dan mimpi yang terpecah-pecah, ia terlempar kembali ke malam yang ingin dikuburnya dalam-dalam.
Malam ketika dunia runtuh.
Ia mendengar suara kaca pecah. Lalu desingan angin.
Dan kemudian… jeritan pelan. Bukan jerit ketakutan, tapi jerit kesakitan yang ditahan. Suara lelaki yang dikenalnya lebih dari siapa pun—Satya Negara.
Ambar berdiri di koridor rumah, tubuhnya gemetar, langkahnya pelan menuju ruang kerja. Setiap jejak terasa berat. Setiap napas menyesakkan. Tapi ia tahu: sesuatu terjadi. Sesuatu yang tak akan bisa dihapus waktu.
Ketika ia tiba di depan pintu ruang kerja, pintu itu terbuka setengah. Cahaya temaram dari lampu meja menyinari sebagian ruangan… dan di sanalah suaminya berada.
Irjen Satya Negara, tubuhnya tersungkur di lantai, bersimbah darah.
Lima lelaki bertopeng berdiri mengelilinginya, tubuh mereka menjulang, gerakannya senyap tapi penuh niat membunuh. Tak ada simbol. Tak ada lambang institusi. Tapi mereka bukan penjahat jalanan—mereka ini terlatih.
Salah satu dari mereka menendang tubuh Satya, memaksa lelaki itu menatap ke atas. Wajah Satya penuh luka, tapi matanya tetap menyala. Tidak dengan ketakutan… tapi kemarahan.
“Pengkhianat,” ujar salah satu dari mereka, suaranya dingin, tanpa emosi.
Satya meludah. Darah mengalir dari sudut bibirnya.
“Aku setia pada tanah ini… bukan pada kalian.”
Lelaki lain, bertopeng hitam pekat, mencengkeram kerah baju dinas Satya yang sobek. Ia mendekat, dan dari balik topengnya, suaranya menggeram rendah.
“Perintah datang dari pemimpin tertinggi negeri ini. Kau dianggap ancaman. Nasionalismemu… sudah usang.”
Ambar tak bisa bergerak. Ia ingin berteriak, ingin menerobos masuk—tapi tubuhnya membeku. Seperti ada yang menahan dari belakang, entah itu ketakutan… atau kebenaran yang terlalu menyakitkan.
Satya masih mencoba berdiri. Lututnya gemetar, tapi ia bertahan.
“Aku bukan ancaman. Aku adalah cermin. Kalian takut karena aku memantulkan wajah asli kalian.”
Satu lagi pukulan menghantam rahangnya.
Satya jatuh lagi. Darah menetes dari dahinya ke lantai.
Lima lelaki bertopeng berdiri sejajar. Salah satunya membuka sarung tangannya sebentar. Di telapak tangan kirinya, sebuah tato—huruf kanji Jepang, hitam pekat, seperti dicap ke kulit.
Ambar menatap tanda itu. Terpaku. Tak bisa lupa.
Sejurus kemudian, suara tembakan memecah malam. Satu peluru, langsung ke jantung.
Satya Negara tak sempat mengucapkan kata terakhir.
Tubuhnya rebah. Mata terbuka, kosong menatap langit-langit. Satu nyawa yang jujur… padam di tangan kejahatan yang menyaru sebagai negara.
Ambar menjerit. Akhirnya. Tapi tak ada yang mendengar.
Ia tersentak dari mimpi itu, napasnya memburu, tubuhnya tetap tak mampu bergerak—karena ia belum sadar, karena ia masih terpenjara dalam koma.
Tapi di dalam sana, di balik kelopak matanya yang tertutup, satu nama terukir dalam api:
Kenanga.
Dan satu janji, tertulis dalam darah:
Kebenaran tak akan mati bersama Satya Negara.
****
Ruang kerja dr. Indrayana sunyi. Lampu meja dengan cahaya kuning redup menebarkan bayangan panjang yang menari-nari di dinding.
Suara jarum jam berdetak pelan, seolah menjadi satu-satunya saksi bisu dalam pertemuan yang penuh beban ini.
Tumpukan berkas dan foto-foto lusuh berserakan di atas meja, menjadi saksi bisu perjalanan tragis keluarga Kenanga.
Aroma kopi yang belum sempat tersentuh menyelimuti udara, tapi tak mampu mengusir ketegangan yang menekan setiap sudut ruangan.
Kenanga duduk di kursi, tubuhnya tegang, namun matanya kosong menatap dokumen di depannya. Ia seperti tenggelam dalam pusaran masa lalu yang getir, kenangan yang seolah menghisap energi dari dalam dirinya.
Di sampingnya, Reno duduk diam, mulut terkatup rapat, pikirannya entah ke mana. Puspita, yang selama ini setia mendampingi Ambar, kini memecah keheningan dengan suara pelan penuh beban.
“Ambar… ibu Kenanga… dia sering bercerita saat masih sadar, walau cuma sesekali,” ujar Puspita, suaranya bergetar halus.
“Walaupun Alzheimer sudah sangat parah, ada malam-malam saat ingatannya kembali sesaat. Dia mengingat masa-masa sebelum semuanya hancur. Tentang suaminya, ayah Kenanga, Irjen Satya Negara.”
Kenanga mengangkat wajah, tatapannya penuh harap sekaligus penasaran.
“Ambar bilang, ayahmu bukan hanya seorang perwira biasa,” lanjut Puspita dengan suara yang seolah enggan melepaskan luka lama itu. “Dia adalah pria yang menjunjung tinggi kehormatan dan nasionalisme.
Seorang pejuang yang rela berkorban demi negara. Tapi, malam itu…” Puspita terdiam sesaat, mengumpulkan keberanian.
“Lima lelaki bertopeng datang ke rumah mereka. Mereka membunuh ayahmu. Dengan kejam, tanpa ampun.”
Suara Puspita melemah, seolah berat untuk mengucapkan setiap kata itu. Namun Kenanga tetap diam, menunggu, memaksa dirinya menyerap tiap detail.
“Ada sesuatu yang khas dari lelaki-lelaki itu,” Puspita melanjutkan, matanya seakan memutar kembali kejadian kelam itu di pikirannya.
“Mereka punya tato di telapak tangan. Huruf Kanji Jepang. Ambar bilang itu semacam tanda kematian, lambang kutukan yang melekat pada mereka yang melakukan hal-hal keji itu.”
Kenanga menunduk, jari-jarinya mengepal erat di atas lutut. Suasana ruang menjadi berat, seperti setiap kata yang keluar dari mulut Puspita menambah beban di dada mereka.
“Tapi…” Kenanga memecah hening, suaranya rendah namun penuh kepastian. “Malam ini, lima lelaki bertopeng yang menyerang ibu, aku yakin mereka bukan yang sama.
Ada perbedaan dalam cara mereka bertindak. Lebih kasar, lebih gegabah. Mereka seperti orang-orang yang terdesak, berbeda dengan lima lelaki bertopeng itu.”
Reno mengangguk pelan, menambahkan, “Tapi ciri tato Kanji itu… itu yang membuat semuanya terhubung. Ini bukan kebetulan.”
Puspita menghela napas panjang. “Ambar pernah mendengar percakapan mereka, saat dia masih kuat. Mereka bilang, pembunuhan ayahmu adalah perintah dari ‘pemimpin tertinggi negeri ini’. Mereka menuduh ayahmu sebagai penghianat negara, yang tak bisa diampuni.”
Ketegangan dalam ruang itu semakin pekat. Suara detik jam berdetak semakin keras di telinga Kenanga, mengingatkan betapa waktu terus berjalan, dan musuh-musuh itu masih berkeliaran, membiarkan luka itu menganga.
Tiba-tiba, pintu ruang kerja diketuk perlahan. Kinan masuk dengan napas tersengal, wajahnya panik. “Kenanga, ada masalah,” katanya tergesa-gesa.
“Maksum, saksi kunci dalam kasus dokumen palsu yang hilang itu… dia kabur dari perawatan rumah sakit. Tidak ada jejaknya.”
Mata Kenanga membulat, jantungnya berdetak semakin kencang, seperti mendengar dentuman perang yang mendekat.
“Ini bukan sekadar kebetulan,” katanya dengan suara berat, penuh kemarahan yang tersimpan lama. “Semua ini saling terhubung — kematian ayahku, serangan malam ini pada ibu, kasus dokumen palsu, dan sekarang hilangnya Maksum.”
Puspita memandang Kenanga dengan mata penuh harap, sekaligus ketakutan. “Apa yang akan kau lakukan sekarang?”
Kenanga berdiri, menatap ke luar jendela yang menampilkan gelap pekat malam tanpa bintang, seolah langit itu pun ikut bersekongkol menyembunyikan rahasia kelam negeri ini.
“Satu hal yang pasti,” katanya, suaranya rendah dan penuh tekad. “Aku akan mengungkap semuanya, sampai akar-akarnya. Aku akan pastikan mereka yang bertanggung jawab harus membayar, sampai titik darah penghabisan.”
Dia kembali menatap mereka, dengan mata yang membara, penuh api perlawanan.
Dalam keheningan itu, terdengar suara detak jam yang tak pernah berhenti, mengingatkan mereka bahwa waktu terus berjalan. Dan dalam kegelapan malam, sebuah janji terpatri: keadilan akan dicari, dan balas dendam akan datang.
*****
Kenanga menghela napas panjang saat pintu ruang perawatan ibunya tertutup rapat di belakangnya. Suara detak mesin monitor dan aroma antiseptik masih membekas di hidungnya.
Langkahnya berat menuruni lorong rumah sakit yang remang, suasana seolah melambat di bawah tekanan malam yang penuh rahasia.
Dia baru saja meninggalkan diskusi yang menegangkan dengan dr. Indrayana dan Puspita, mendengar kisah tragis masa lalu yang mulai menyusun potongan teka-teki keluarganya.
Namun, jawaban yang dia cari masih tersembunyi dalam bayang-bayang.
Ketika ia keluar ke udara malam yang dingin, ponselnya bergetar di saku jaketnya. Layar menyala menampilkan nama yang tak asing: “Lelaki Berjaket Hitam.”
Detak jantung Kenanga langsung berpacu. Ia mengangkat telepon dengan tangan sedikit bergetar.
“Saatnya kau turun ke Eclipse,” suara di ujung telepon itu berat dan penuh wibawa, tanpa memberi ruang untuk tawar-menawar. “Ada bartender bernama Angga yang bisa memberi kita petunjuk tentang Winda Marlina.”
Kenanga menatap ke gelap malam, sorot matanya tajam. “Kenapa Winda Marlina? Apa hubungan dia dengan kasus ini?”
“Dia lebih dekat dengan Kurnia Praja daripada yang kau tahu. Kita butuh informasi yang hanya dia bisa berikan,” jawab lelaki itu singkat.
Kenanga mengangguk meski lawannya tak bisa melihatnya. “Aku akan ke sana.”
Telepon terputus.
Di tengah gemuruh kendaraan dan lampu kota yang berkelip, Kenanga berubah. Ia membiarkan dirinya menyatu dengan gelap, mengenakan kembali topeng yang selama ini menyembunyikan kemarahannya: penari klub malam, pengintai bayangan.
Saat tiba di ‘Eclipse’, musik berdentum keras dan lampu strobo menari liar di dinding. Kenanga bergerak mengikuti irama, setiap gerakan terukur namun memikat, menebar pesona yang tak terduga. Tubuhnya lentur, penuh rahasia dan janji tersembunyi.
Di balik bar, Angga berdiri dengan sikap tenang tapi waspada, matanya tajam mengawasi. Kenanga mendekat perlahan, senyum mengembang tipis, bisikan menggoda terukir di bibirnya.
“Kau pasti Angga,” suaranya lembut, tapi penuh magnetisme. “Aku baru di sini, ingin tahu lebih banyak tentang siapa yang bermain di dunia ini.”
Angga memandang dingin, namun ada sedikit penasaran yang bersinar. “Kalau kau ingin tahu, jangan cuma berdiri di sini. Ikuti aku.”
Kenanga menatapnya dalam, hampir berbisik. “Aku dengar nama Winda Marlina. Katanya dia sosialita yang dekat dengan Kurnia Praja.”
Tatapan Angga berubah, ada rasa waspada dan ketegangan yang muncul tiba-tiba. “Winda bukan orang sembarangan. Dia punya banyak rahasia gelap. Rahasia yang bisa membunuh.”
Kenanga menahan napas, mengarahkan matanya ke Angga, menunggu setiap kata yang bisa membimbingnya. “Di mana dia tinggal? Aku harus tahu, demi keselamatan ibuku.”
Angga melirik sekeliling, memastikan tak ada yang mendengar. Dia mengeluarkan secarik kertas kecil, lalu menyerahkannya dengan gerakan pelan. “Menteng. Apartemen mewah. Tapi hati-hati, ini bukan permainan biasa. Ada yang mengintai.”
Kenanga menerima kertas itu dengan jari-jari yang menggenggam erat, sementara musik klub berdentum di telinganya seperti detak jantung yang tak bisa ia hentikan.
Setelah menjauh dari keramaian, Kenanga mencari tempat sepi di pojok klub. Ia membuka ponselnya, mengetik pesan berisi alamat apartemen Winda Marlina, lalu mengirimkannya ke nomor lelaki berjaket hitam.
Pesan terkirim.
******
Langkah kakinya nyaris tanpa suara saat lelaki itu berdiri di seberang jalan, mengenakan jaket hitam lusuh yang menyatu dengan bayangan malam.
Di bawah cahaya redup lampu kota, matanya menyorot tajam ke arah mobil mewah berwarna hitam metalik yang baru saja berhenti di depan sebuah apartemen elit di kawasan pusat kota.
Dari dalam mobil, seorang wanita muda turun dengan gerakan anggun. Tumit tinggi berdetak ringan di atas trotoar marmer. Rambutnya disanggul rapi, gaun malam yang memeluk tubuhnya memancarkan aroma kemewahan. Winda Marlina.
Tiga pria bersetelan gelap mengikutinya. Tubuh mereka tegap. Pandangan mereka mengamati sekeliling, siaga seperti kawanan anjing penjaga yang tak butuh perintah.
Tapi malam ini, tidak ada peringatan yang cukup.
Lelaki berjaket hitam bergerak begitu Winda menghilang ke balik pintu lift. Bayangan tubuhnya melintas di lorong belakang gedung, cepat dan senyap. Ia tahu persis ke mana harus melangkah.
Pengawal pertama bahkan tak sempat menarik napas saat lengan kekar membungkus lehernya dari belakang, memutus aliran napas dalam tiga detik. Tubuhnya diletakkan dengan hati-hati di balik lemari linen.
Pengawal kedua mencoba berbalik, tapi siku menghantam ulu hatinya, membuatnya terbungkuk. Pukulan telak ke tengkuk meruntuhkannya dalam sekejap.
Pengawal ketiga lebih awas. Ia sempat menghunus pisau kecil dari dalam jaket, tapi gerakan lelaki berjaket hitam lebih cepat.
Sebuah tendangan berputar menghantam rahangnya, diikuti pukulan kombinasi yang menghentikan perlawanan. Tubuhnya jatuh menabrak vas keramik mahal, pecah berantakan.
Di lantai delapan belas, Winda membuka pintu apartemennya dengan remote sidik jari. Langkahnya ringan, seperti biasa. Musik jazz mengalun pelan dari speaker dinding.
Ia menggantung clutch kecilnya, berjalan ke meja bar—dan terdiam.
Lelaki itu sudah duduk di kursi dapur, wajahnya tertutup bayangan. Satu tangan memegang koper hitam kecil, dengan logo timbul “BGS Fondation” di sudutnya.
Winda tersentak, matanya membelalak.
“Apa kau gila—bagaimana bisa kau masuk ke sini?”
Lelaki itu tidak menjawab. Ia hanya menatap tajam.
“Aku butuh kode koper ini,” katanya datar.
“Aku… aku tidak tahu. Sumpah.”
“Kau tahu,” sahutnya, lebih dingin.
Ia meletakkan sesuatu di meja—sebuah foto lama. Winda mengenalinya. Itu dirinya. Masih SMA. Berdiri di depan sebuah panti asuhan, tersenyum polos.
“Bagaimana kau bisa dapat foto itu?”
“Saya tahu tentang ayah tirimu di Sumedang. Tentang utang judi yang memaksamu kabur dari rumah. Tentang malam kau pertama kali dijual ke seorang pejabat hotel di Bandung.”
Winda gemetar. Kepalanya perlahan menggeleng.
“Kau tidak mengerti apa yang aku hadapi…”
“Aku tidak perlu mengerti. Aku hanya perlu kodenya.”
Sunyi menyelimuti ruangan beberapa detik. Nafas Winda mulai tak teratur. Matanya berkaca-kaca.
“Kau pikir aku mau jadi seperti ini? Aku hanya… aku hanya ingin hidup. Mereka menjanjikan segalanya, lalu mengancam. Kurnia… dia memperkenalkan aku ke Bagaspati. Lalu semua jadi lebih gelap.”
“Kode, Winda.”
“Aku akan bantu,” bisiknya akhirnya. “Tapi… ada yang harus kau tahu.”
Lelaki itu menunggu, matanya tidak berkedip.
“Bagaspati… dia memang monster. Tapi dia bukan dalangnya.”
Diam.
“Semua ini… bukan hanya tentang dokumen. Ini jauh lebih dalam. Bahkan Kurnia Praja hanya bidak. Ada satu nama—yang mereka semua takuti. Dia orang… yang tak akan kau kira.”
Lelaki itu maju sedikit. Matanya menajam.
“Siapa?”
Winda menatapnya, ragu-ragu. Mulutnya mulai membuka—
BRAKK!
Jendela balkon tiba-tiba pecah. Winda terhuyung.
Darah muncrat dari sisi kepalanya. Tubuhnya jatuh ke belakang, menghantam meja kaca, menghancurkan vas, dan terdiam selamanya.
Lelaki berjaket hitam sudah bergerak sebelum tubuh Winda menyentuh lantai. Ia berlindung di balik lemari baja, matanya menyorot ke arah balkon. Satu peluru. Presisi. Itu bukan kerjaan amatir.
Dari kejauhan, suara alarm apartemen menyala. Ia bergerak cepat—menyalakan sistem penghapus jejak dari ponsel, membakar beberapa lembar dokumen, lalu mengangkat koper.
Sebelum pergi, ia menatap jenazah Winda satu detik lebih lama. Matanya tidak menunjukkan emosi, tapi rahangnya mengeras.
Ia meninggalkan ruangan senyap itu.
Dan di belakangnya, misteri semakin dalam.
*******
Lelaki berjaket hitam tidak bergerak selama dua detik. Cukup untuk memastikan satu hal—penembak itu bukan amatiran.
Satu peluru.
Satu jiwa.
Satu pesan.
Dia bergeser cepat, membalik meja kaca dengan satu sentakan. Suara pecahannya mengiringi langkah pelan menuju jendela—asal datangnya peluru. Tapi yang dilihatnya hanya cahaya lampu kota yang berkedip di kejauhan, samar seperti dusta dalam pidato pejabat.
Tak ada bayangan.
Tak ada pantulan.
Hanya kematian yang diam.
Ia kembali ke tubuh Winda. Di tangannya masih tergenggam secarik kertas, diremas separuh dalam ketakutan sebelum ajal menjemput. Ia tarik perlahan dari jari-jari yang mulai dingin.
Isinya hanya satu nama. Ditulis terburu-buru, nyaris tak terbaca. Tapi cukup untuk membuat jantungnya menegang.
Seseorang yang tak pernah disebut.
Langkah kaki terdengar dari lorong luar. Teratur. Berat. Tiga… empat… lima pasang.
Sudah datang.
Dia tahu waktunya hampir habis.
Dengan satu gerakan, ia mengambil koper yang telah terbuka—isinya tak tergantikan. Lalu mematikan semua lampu. Sunyi mengurung apartemen, seperti liang tak bertanda.
Tapi sebelum ia melompat ke balkon dan menghilang ke kegelapan, ia sempat menoleh ke tubuh Winda.
Perempuan itu menyimpan banyak dosa.
Tapi malam ini, ia mati dalam kebenaran.
Di kejauhan, suara sirene menggema. Tapi bukan menuju penyelamatan.
Lelaki berjaket hitam membuka ponsel burner-nya.
Ia mengetik pelan.
Pesan terkirim ke satu nama di daftar: Kenanga.
“Winda sudah mati. Tapi dia sempat menyebut satu nama. Kita salah mengira pusat kekuatan. Bersiaplah.”
“Aku akan datang. Bawa semua yang kau punya.”
Layar ponsel padam.
Langit kota malam itu seolah retak oleh rahasia yang menolak diam. Dan perang yang lebih besar baru saja dibuka.
Dalam perang bayangan, yang paling berbahaya bukan yang terlihat. Tapi yang tak pernah disebut.
Dan kali ini, Kenanga harus memilih: kebenaran… atau hidupnya sendiri. Nantikan kisah selanjutnya di JEJAK KENANGA 6.
*Cerita ini fiksi. Nama, tempat, dan peristiwa hanyalah imajinasi. Jika ada kesamaan, itu kebetulan belaka.